BAB-I
PENGANTAR FIQH ISLAM
PENGANTAR FIQH ISLAM
Pengertian Fiqh Islam.
Fiqih Islam dalam bahasa Arab disebut dengan al-Fiqh al-Islamiy.
Istilah diatas memakai bentuk na’at-man’ut (shifat-maushuf). Dalam hal ini, kata al-islamiy mensifati kata al-fiqh. Secara etimologis, al-fiqh bermakna pemahaman yang mendalam.
- Secara terminologis, Fiqih Islam ialah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang embe-hukum islam yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci. Pentingnya Mempelajari Fiqih Islam Allah telah menetapkan embe dari segala sesuatu dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Para ahli ushul fiqih kemudian menggali pokok-pokok pemahaman dari teks-teks yang ada pada keduanya. Dengan memanfaatkan jerih payah para ahli ushul fiqih tersebut, para ahli fiqih kemudian menjelaskan embe dari segala sesuatu. Penjelasan-penjelasan tersebut tertuang dalam Fiqih Islam. Jadi dengan mempelajari Fiqih Islam, kita akan mengetahui embe dari segala sesuatu, sehingga kita emb menjalani kehidupan sesuai dengan embe-hukum tersebut. Dengan menjalani kehidupan sesuai dengan embe-hukum Allah tersebut, kita akan selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Keutamaan Mempelajari Fiqih Islam
- Dengan mempelajari Fiqih Islam, kita akan menjadi orang yang berilmu karena mengetahui embe-hukum agama. Kalau kita telah menjadi orang yang berilmu, maka kita akan memiliki banyak kelebihan dan keutamaan diatas orang-orang yang tidak berilmu. Allah berfirman :“Katakanlah : Apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu?”(QS Az-Zumar: 9)
- Sebaik-baik hamba Allah ialah yang paling takut kepada-Nya. Seseorang tidak akan memiliki rasa takut kepada Allah kecuali jika dia itu orang yang berilmu. Allah berfirman: “Yang takut kepada Allah diantara para hamba-Nya hanyalah orang-orang yang berilmu.” (QS Faathir: 28)
- Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Allah berfirman: “Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang dikaruniai ilmu.” (QS Al-Mujadalah : 11)
- Allah memerintahkan bahwa sebagian diantara orang-orang mukmin harus ada yang memperdalam agamanya, untuk kemudian ember peringatan kepada saudara-saudaranya ember mukmin yang lain. Allah berfirman: “Mengapa tidak pergi dari setiap kelompok diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan tentang din dan untuk ember peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri.” (QS At-Taubah 122)
- Rasulullah bersabda,”Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan atasnya, maka Allah akan menjadikannya paham dalam masalah agamanya” (HR Bukhari-Muslim, dari Muawiyah ra). Ketentuan-ketentuan Umum dalam Mempelajari Fiqih Islam
- Dilarang membahas hal-hal yang belum terjadi sampai benar-benar terjadi.
- Hendaknya menjauhkan diri dari terlalu banyak bertanya dan berbelit-belit.
- Hendaknya menjauhkan diri dari perbedaan dan perpecahan dalam agama.
- Hendaknya mengembalikan masalah-masalah yang diperselisihkan kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah.
FUQAHA BESAR DARI KALANGAN PARA SAHABAT
Yang Terbanyak Berfatwa
- Umar ibnul Khaththab
- Ali ibn Abi Thalib
- Abdullah ibn Mas’ud
- ‘Aisyah Ummul Mukminin
- Zaid ibn Tsabit
- Abdullah ibn Abbas
- Abdullah ibn Umar
Yang Jumlah Fatwanya Pertengahan
- Abu Bakr Ash-Shiddiq
- Ummu Salamah
- Anas ibn Malik
- Abu Sa’id Al-Khudri
- Abu Hurairah
- ‘Utsman ibn ‘Affan
- Abdullah ibn ‘Amr ibnul ‘Ash
- Abdullah ibn Zubair
- Abu Musa Al-Asy’ari
- Sa’d ibn Abi Waqqash
- Salman Al-Farisi
- Jabir ibn ‘Abdillah
- Mu’adz ibn Jabbal
Dari Kalangan Tabi’in Fuqaha Madinah
- Sa’id ibnul Musayyab
- ‘Urwah ibn Zubair
- Al-Qasim ibn Muhammad
- Khaarijah ibn Zaid
- Abu Bakr ibn Abdir Rahman
- Sulaiman ibn Yasar
- ‘Ubaidullah ibn Abdillah
Dari Fuqaha Mekah
- ‘Athaa’ ibn Abi Rabbah
- Thawus ibn Kaisan
- Mujahid ibn Jabar
- ‘Ubaid ibn ‘Umair
- ‘Amr ibn Dinar
- Abdullah ibn Abi Mulaikah
- Abdur Rahman ibn Saabith
Ikrimah Fuqaha Bashrah
- ‘Amr ibn Salamah
- Abu Maryam Al-Hanafi
- Ka’b ibn Saud
- Al-Hasan Al-Bashri
- Muhammad ibn Siiriin
Fuqaha Kufah (Para Murid Ali dan Ibn Mas’ud)
- ‘Alqamah ibn Qays An-Nakha’i
- Al-Aswad ibn Yazid An-Nakha’i
- Masruq ibnul Ajda’ Al-Hamdani
- Syuraih ibnul Haarits Al-Qadhi
- Abu Hanifah An-Nu’man ibn Tsabit
- Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi ‘Aamir
- Muhammad ibn Idris ibnul ‘Abbas Asy-Syafi’i
- Ahmad ibn Hanbal
- Sufyan Ats-Tsauri
- Al-Auza’i
- Al-Laitsi
- Dawud Azh-Zhahiri
BAB-II
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP USHUL FIQIH
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP USHUL FIQIH
Pengetahuan Fiqh itu lahir melalui proses pembahasan yang digariskan dalam ilmu ushul Fiqh. Menurut aslinya kata "Ushul Fiqh" adalah kata yang berasal dari bahasa Arab "Ushulul Fiqh" yang berarti asal-usul Fiqh. Maksudnya, pengetahuan Fiqh itu lahir melalui proses pembahasan yang digariskan dalam ilmu ushul Fiqh. Pengetahuan Fiqh adalah formulasi dari nash syari'at yang berbentuk Al-Qur'an, Sunnah Nabi dengan cara-cara yang disusun dalam pengetahuan Ushul Fiqh. Meskipun cara-cara itu disusun lama sesudah berlalunya masa diturunkan Al-Qur'an dan diucapkannya sunnah oleh Nabi, namun materi, cara dan dasar-dasarnya sudah mereka (para Ulama Mujtahid) gunakan sebelumnya dalam mengistinbathkan dan menentukan hukum. Dasar-dasar dan cara-cara menentukan hukum itulah yang disusun dan diolah kemudian menjadi pengetahuan Ushul Fiqh.
Menurut Istitah yang digunakan oleh para ahli Ushul Fiqh ini, Ushul Fiqh itu ialah, suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syari'at Islam dari sumbernya. Dalam pemakaiannya, kadang-kadang ilmu ini digunakan untuk menetapkan dalil bagi sesuatu hukum; kadang-kadang untuk menetapkan hukum dengan mempergunakan dalil Ayat-ayat Al-Our'an dan Sunnah Rasul yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, dirumuskan berbentuk "hukum Fiqh" (ilmu Fiqh) supaya dapat diamalkan dengan mudah. Demikian pula peristiwa yang terjadi atau sesuatu yang ditemukan dalam kehidupan dapat ditentukan hukum atau statusnya dengan mempergunakan dalil. Yang menjadi obyek utama dalam pembahasan Ushul Fiqh ialah Adillah Syar'iyah (dalil-dalil syar'i) yang merupakan sumber hukum dalam ajaran Islam. Selain dari membicarakan pengertian dan kedudukannya dalam hukum Adillah Syar'iyah itu dilengkapi dengan berbagai ketentuan dalam merumuskan hukum dengan mempergunakan masing-masing dalil itu. Topik-topik dan ruang lingkup yang dibicarakan dalam pembahasan ilmu Ushul Fiqh ini meliputi:
- Bentuk-bentuk dan macam-macam hukum, seperti hukum taklifi (wajib, sunnat, mubah, makruh, haram) dan hukum wadl'i (sabab, syarat, mani', 'illat, shah, batal, azimah dan rukhshah).
- Masalah perbuatan seseorang yang akan dikenai hukum (mahkum fihi) seperti apakah perbuatan itu sengaja atau tidak, dalam kemampuannya atau tidak, menyangkut hubungan dengan manusia atau Tuhan, apa dengan kemauan sendiri atau dipaksa, dan sebagainya.
- Pelaku suatu perbuatan yang akan dikenai hukum (mahkum 'alaihi) apakah pelaku itu mukallaf atau tidak, apa sudah cukup syarat taklif padanya atau tidak, apakah orang itu ahliyah atau bukan, dan sebagainya.
- Keadaan atau sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum ini meliputi keadaan yang disebabkan oleh usaha manusia, keadaan yang sudah terjadi tanpa usaha manusia yang pertama disebut awarid muktasabah, yang kedua disebut awarid samawiyah.
- Masalah istinbath dan istidlal meliputi makna zhahir nash, takwil dalalah lafazh, mantuq dan mafhum yang beraneka ragam, 'am dan khas, muthlaq dan muqayyad, nasikh dan mansukh, dan sebagainya.
- Masalah ra'yu, ijtihad, ittiba' dan taqlid; meliputi kedudukan rakyu dan batas-batas penggunannya, fungsi dan kedudukan ijtihad, syarat-syarat mujtahid, bahaya taqlid dan sebagainya.
- Masalah adillah syar'iyah, yang meliputi pembahasan Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas, istihsan, istishlah, istishhab, mazhabus shahabi, al-'urf, syar'u man qablana, bara'atul ashliyah, sadduz zari'ah, maqashidus syari'ah/ususus syari'ah.
- Masa'ah ra'yu dan qiyas; meliputi. ashal, far'u, illat, masalikul illat, al-washful munasib, as-sabru wat taqsim, tanqihul manath, ad-dauran, as-syabhu, ilghaul fariq; dan selanjutnya dibicarakan masalah ta'arudl wat tarjih dengan berbagai bentuk dan penyelesaiannya.
Sesuatu yang tidak boleh dilupakan dalam mempelajari Ushui Fiqh ialah bahwa peranan ilmu pembantu sangat menentukan proses pembahasan. Dalam pembicaraan dan pembahasan materi Ushul Fiqh sangat diperlukan ilmu-ilmu pembantu yang langsung berperan, seperti ilmu tata bahasa Arab dan qawa'idul lugahnya, ilmu mantiq, ilmu tafsir, ilmu hadits, tarikh tasyri'il islami dan ilmu tauhid. Tanpa dibantu oleh ilmu-ilmu tersebut, pembahasan Ushul Fiqh tidak akan menemui sasarannya. Istinbath dan istidlal akan menyimpan dari kaidahnya. Ushul Fiqh itu ialah suatu ilmu yang sangat berguna dalam pengembangan pelaksanaan syari'at (ajaran Islam). Dengan mempelajari Ushul Fiqh orang mengetahui bagaimana Hukum Fiqh itu diformulasikan dari sumbernya.
Dengan itu orang juga dapat memahami apa formulasi itu masih dapat dipertahankan dalam mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan sekarang; atau apakah ada kemungkinan untuk direformulasikan. Dengan demikian, orang juga dapat merumuskan hukum atau penilaian terhadap kenyataan yang ditemuinya sehari-hari dengan ajaran Islam yang bersifat universal itu. Dengan Usul Fiqh, maka:
- Ilmu Agama Islam akan hidup dan berkembang mengikuti perkembangan peradaban umat manusia.
- Statis dan jumud dalam ilmu pengetahuan agama dapat dihindarkan.
- Orang dapat menghidangkan ilmu pengetahuan agama sebagai konsumsi umum dalam dunia pengetahuan yang selalu maju dan berkembang mengikuti kebutuhan hidup manusia sepanjang zaman.
- Sekurang-kurangnya, orang dapat memahami mengapa para Mujtahid zaman dulu merumuskan Hukum Fiqh seperti yang kita lihat sekarang. Pedoman dan norma apa saja yang mereka gunakan dalam merumuskan hukum itu. Kalau mereka menemukan sesuatu peristiwa atau benda yang memerlukan penilaian atau hukum Agama Islam, apa yang mereka lakukan untuk menetapkannya; prosedur mana yang mereka tempuh dalam menetapkan hukumnya. Dengan demikian orang akan terhindar dari taqlid buta; kalau tidak dapal menjadi Mujtahid, mereka dapat menjadi Muttabi' yang baik, (Muttabi' ialah orang yang mengikuti pendapat orang dengan mengetahui asal-usul pendapat itu).
Dengan demikian, berarti bahwa Ilmu Ushul Fiqh merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam pengembangan dan pengamalan ajaran Islam di dunia yang sibuk dengan perubahan menuju modernisasi dan kemajuan dalam segala bidang. Melihat demikian luasnya ruang lingkup materi Ilmu Ushul Fiqh, tentu saja tidak semua perguruan/lembaga dapat mempelajarinya secara keseluruhan.
BAB-III
OBJEK PEMBAHASAN ILMU USHUL FIQIH
OBJEK PEMBAHASAN ILMU USHUL FIQIH
Objek pembahasan dari Ushul fiqh meliputi tentang dalil, hukum, kaidah dan ijtihad. Sesuai dengan keterangan tentang pengertian Ilmu Ushul Fiqh di depan, maka yang menjadi obyek pembahasannya, meliputi:
Pembahasan Tentang Dalil.
Pembahasan tentang dalil dalam ilmu Ushul Fiqh adalah secara global. Di sini dibahas tentang macam-macamnya, rukun atau syarat masing-masing dari macam-macam dalil itu, kekuatan dan tingkatan-tingkatannya. Jadi di dalam Ilmu Ushul Fiqh tidak dibahas satu persatu dalil bagi setiap perbuatan.
Pembahasan tentang dalil dalam ilmu Ushul Fiqh adalah secara global. Di sini dibahas tentang macam-macamnya, rukun atau syarat masing-masing dari macam-macam dalil itu, kekuatan dan tingkatan-tingkatannya. Jadi di dalam Ilmu Ushul Fiqh tidak dibahas satu persatu dalil bagi setiap perbuatan.
Pembahasan Tentang Hukum
Pembahasan tentang hukum dalam Ilmu Ushul Fiqh adalah secara umum, tidak dibahas secara terperinci hukum bagi setiap perbuatan. Pembahasan tentang hukum ini, meliputi pembahasan tentang macam-macam hukum dan syarat-syaratnya. Yang menetapkan hukum (al-hakim), orang yang dibebani hukum (al-mahkum 'alaih) dan syarat-syaratnya, ketetapan hukum (al-mahkum bih) dan macam-macamnya dan perbuatan-perbuatan yang ditetapi hukum (al-mahkum fih) serta syarat-syaratnya.
Pembahasan Tentang Kaidah.
Pembahasan tentang kaidah yang digunakan sebagai jalan untuk memperoleh hukum dari dalil-dalilnya antara lain mengenai macam-macamnya, kehujjahannya dan hukum-hukum dalam mengamalkannya.
Pembahasan Tentang Ijtihad.
Dalam pembahasan ini, dibicarakan tentang macam-macamnya, syarat-syarat bagi orang yang boleh melakukan ijtihad, tingkatan-tingkatan orang dilihat dari kaca mata ijtihad dan hukum melakukan ijtihad.
Pembahasan tentang hukum dalam Ilmu Ushul Fiqh adalah secara umum, tidak dibahas secara terperinci hukum bagi setiap perbuatan. Pembahasan tentang hukum ini, meliputi pembahasan tentang macam-macam hukum dan syarat-syaratnya. Yang menetapkan hukum (al-hakim), orang yang dibebani hukum (al-mahkum 'alaih) dan syarat-syaratnya, ketetapan hukum (al-mahkum bih) dan macam-macamnya dan perbuatan-perbuatan yang ditetapi hukum (al-mahkum fih) serta syarat-syaratnya.
Pembahasan Tentang Kaidah.
Pembahasan tentang kaidah yang digunakan sebagai jalan untuk memperoleh hukum dari dalil-dalilnya antara lain mengenai macam-macamnya, kehujjahannya dan hukum-hukum dalam mengamalkannya.
Pembahasan Tentang Ijtihad.
Dalam pembahasan ini, dibicarakan tentang macam-macamnya, syarat-syarat bagi orang yang boleh melakukan ijtihad, tingkatan-tingkatan orang dilihat dari kaca mata ijtihad dan hukum melakukan ijtihad.
BAB-IV
SEJARAH PERTUMBUHAN ILMU USHUL FIQH
SEJARAH PERTUMBUHAN ILMU USHUL FIQH
Ilmu Ushul Fiqh adalah kaidah-kaidah yang digunakan dalam usaha untuk memperoleh hukum-hukum syara' tentang perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.Dan usaha untuk memperoleh hukum-hukum tersebut, antara lain dilakukan dengan jalan ijtihad. Sumber hukum pada masa Rasulullah SAW hanyalah Al-Qur'an dan As-Sunnah (Al-Hadits). Dalam pada itu kita temui diantara sunnah-sunnahnya ada yang memberi kesan bahwa beliau melakukan ijtihad. Misalnya, beliau melakukan qiyas terhadap peristiwa yang dialami oleh Umar Bin Khattab RA, sebagai berikut.
Artinya: "Wahai Rasulullah, hari ini saya telah berbuat suatu perkara yang besar; saya mencium isteri saya, padahal saya sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya : Bagaimana pendapatmu, seandainya kamu berkumur-kumur dengan air dikala kamu sedang berpuasa? Lalu saya jawab: tidak apa-apa dengan yang demikian itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: Maka tetaplah kamu berpuasa!" (I'lamul Muwaqqi'in, Juz: I, hal: 199).
Pada hadits di atas Rasulullah SAW menetapkan tidak batal puasa seseorang karena mencium isterinya dengan mengqiyaskan kepada tidak batal puasa seseorang karena berkumur-kumur. Juga seperti hadits Rasulullah SAW:
Artinya: "Seandainya tidak akan memberatkan terhadap umatku, niscaya kuperintahkan kepada mereka bersiwak (bersikat gigi) setiap akan melakukan shalat." (HR. Abu Daud dari Zaid Bin Khalid al-Juhanni).
Diterangkan oleh Muhammad Ali as-Sayis, bahwa hadits tersebut menunjukkan kepada kita adanya pilihan Rasulullah SAW terhadap salah satu urusan, karena untuk menjaga kemaslahatan umatnya. Seandainya beliau tidak diperbolehkan melakukan ijtihad, hal itu tidak akan terjadi. Dalam pada itu, dari penelitian sebagian ulama terhadap berbagai peristiwa hidup Rasulullah SAW, berkesimpulan bahwa beliau bisa melakukan ijtihad dan memberi fatwa berdasarkan pendapatnya pribadi tanpa wahyu, terutama dalam hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan persoalan hukum. Kesimpulan tersebut, sesuai dengan sabda beliau sendiri:
Artinya:"Sungguh saya memberi keputusan diantara kamu tidak lain dengan pendapatku dalam hal tidak diturunkan (wahyu) kepadaku." (HR. Abu Daud dan Ummi Salamah). Rasulullah SAW adalah seorang manusia juga sebagaimana manusia yang lain pada umumnya maka hasil ijtihadnya bisa benar dan bisa salah, sebagaimana diterangkan dalam sebuah riwayat, beliau bersabda:
Artinya: "Saya tidak lain adalah seorang manusia juga, maka segala yang saya katakan kepadamu yang berasal dari Allah adalah benar; dan segala yang saya katakan dari diri saya sendiri, karena tidak lain saya juga seorang manusia, bisa salah bisa benar." (Ijtihad Rasul, hal: 52-53). Hanya saja jika hasil ijtihad beliau itu salah, Allah menurunkan wahyu yang tidak membenarkan hasil ijtihad beliau dan menunjukkan kepada yang benar. Sebagai contoh hasil ijtihad beliau tentang tindakan yang diambil terhadap tawanan perang Badar. Dalam hal ini beliau menanyakan terlebih dahulu kepada para sahabatnya. Menurut Abu Bakar agar mereka (para tawanan perang Badar) dibebaskan dengan membayar tebusan. Sedangkan menurut Umar bin Khattab, mereka harus dibunuh, karena mereka telah mendustakan dan mengusir Rasulullah SAW dari Makkah. Dari dua pendapat tersebut, beliau memilih pendapat Abu Bakar. Kemudian turun ayat Al-Qur'an yang tidak membenarkan pilihan beliau tersebut dan menunjukkan kepada yang benar, yakni:
Artinya: "Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana." (Al-Anfaal: 67). Jika terhadap hasil ijtihad Rasulullah SAW tersebut, tidak diturunkan wahyu yang tidak membenarkan dan menunjukkan kepada yang benar, berarti hasil ijtihad beliau itu benar, dan sudah barang tentu termasuk ke dalam kandungan pengertian As-Sunnah (Al-Hadits). Kegiatan ijtihad pada masa ini, bukan saja dilakukan oleh beliau sendiri, melainkan beliau juga memberi ijin kepada para sahabatnya untuk melakukan ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau dalam menghadapi suatu persoalan yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagaimana yang terjadi ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, yang diterangkan dalam hadits sebagai berikut:
Artinya: "(Rasulullah SAW bertanya): Bagaimana cara kamu memutusi jika datang kepadamu suatu perkara? Ia menjawab: Saya putusi dengan (hukum) yang terdapat dalam kitab Allah. Beliau bertanya: Jika tidak kamu dapati (hukum itu) dalam kitah Allah? Ia menjawab: Maka dengan Sunnah Rasulullah. Beliau bertanya: Jika tidak kamu dapati dalam Sunnah Rasulullah juga dalam kitab Allah? Ia menjawab: Saya akan berijtihad dengan pikiran dan saya tidak akan lengah. Kemudian Rasulullah SAW menepuk dadanya dan bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah SAW yang diridlai oleh Rasulullah." (HR. Abu Daud). Bahkan beliau pernah memerintahkan 'Amr bin 'Ash untuk memberi keputusan terhadap suatu perkara, padahal beliau di hadapannya. Atas perintah itu, lalu 'Amr bertanya kepada beliau.
Artinya: "(Rasulullah SAW bertanya): Bagaimana cara kamu memutusi jika datang kepadamu suatu perkara? Ia menjawab: Saya putusi dengan (hukum) yang terdapat dalam kitab Allah. Beliau bertanya: Jika tidak kamu dapati (hukum itu) dalam kitah Allah? Ia menjawab: Maka dengan Sunnah Rasulullah. Beliau bertanya: Jika tidak kamu dapati dalam Sunnah Rasulullah juga dalam kitab Allah? Ia menjawab: Saya akan berijtihad dengan pikiran dan saya tidak akan lengah. Kemudian Rasulullah SAW menepuk dadanya dan bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah SAW yang diridlai oleh Rasulullah." (HR. Abu Daud). Bahkan beliau pernah memerintahkan 'Amr bin 'Ash untuk memberi keputusan terhadap suatu perkara, padahal beliau di hadapannya. Atas perintah itu, lalu 'Amr bertanya kepada beliau.
Sebagai contoh ijtihad yang dilakukan oleh sahabat, yakni ijtihad yang dilakukan oleh 'Amar bin Yasir, sebagai berikut:
Artinya: "Saya telah berjunub dan tidak mendapatkan air. Maka saya berguling-guling pada debu kemudian saya mengerjakan shalat. Lalu hal itu, saya sampaikan kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda: Sesungguhnya cukup kamu melakukan begini Nabi menepuk tanah dengan dua telapak tangannya kemudian meniupnya, lalu menyapukannya ke wajahnya dan dua telapak tanganya." (HR. Bukhari dan Muslim). Pada hadits di atas, 'Ammar bin Yasir mengqiyaskan debu dan air untuk mandi dalam menghilangkan junubnya, sehingga ia dalam menghilangkan junub karena tidak mendapatkan air itu, dilakukan dengan berguling-guling di atas debu. Namun hasil ijtihadnya ini tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Hasil ijtihad para sahabat tidak dapat dijadikan sumber hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh kaum muslimin, kecuali jika hasil ijtihadnya telah mendapat pengesahan atau pengakuan dari Rasulullah SAW dan tidak diturunkan wahyu yang tidak membenarkannya.
Dari uraian di atas dapat dipetik arti bahwa ijtihad baik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW maupun oleh para sahabatnya pada masa ini tidak merupakan sumber hukum, karena keberadaan atau berlakunya hasil ijtihad kembali kepada wahyu. Akan tetapi dengan adanya kegiatan ijtihad yang terjadi pada masa ini, mempunyai hikmah yang besar, karena hal itu merupakan petunjuk bagi para sahabat dan para ulama dari generasi selanjutnya untuk berijtihad pada masa-masanya dalam menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW atau yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Memang, semenjak masa sahabat telah timbul persoalan-persoalan baru yang menuntut ketetapan hukumnya.
Untuk itu para sahabat berijtihad, mencari ketetapan hukumnya. Setelah wafat Rasulullah SAW sudah barang tentu berlakunya hasil ijtihad para sahabat pada masa ini, tidak lagi disahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dengan demikian semenjak masa sahabat ijtihad sudah merupakan sumber hukum. Sebagai contoh hasil ijtihad para sahabat, yaitu : Umar bin Khattab RA tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada seseorang yang mencuri karena kelaparan (darurat/terpaksa). Dan Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa wanita yang suaminya meninggal dunia dan belum dicampuri serta belum ditentukan maharnya, hanya berhak mendapatkan mut'ah. Ali menyamakan kedudukan wanita tersebut dengan wanita yang telah dicerai oleh suaminya dan belum dicampuri serta belum ditentukan maharnya, yang oleh syara' ditetapkan hak mut'ah baginya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:
Dari uraian di atas dapat dipetik arti bahwa ijtihad baik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW maupun oleh para sahabatnya pada masa ini tidak merupakan sumber hukum, karena keberadaan atau berlakunya hasil ijtihad kembali kepada wahyu. Akan tetapi dengan adanya kegiatan ijtihad yang terjadi pada masa ini, mempunyai hikmah yang besar, karena hal itu merupakan petunjuk bagi para sahabat dan para ulama dari generasi selanjutnya untuk berijtihad pada masa-masanya dalam menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW atau yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Memang, semenjak masa sahabat telah timbul persoalan-persoalan baru yang menuntut ketetapan hukumnya.
Untuk itu para sahabat berijtihad, mencari ketetapan hukumnya. Setelah wafat Rasulullah SAW sudah barang tentu berlakunya hasil ijtihad para sahabat pada masa ini, tidak lagi disahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dengan demikian semenjak masa sahabat ijtihad sudah merupakan sumber hukum. Sebagai contoh hasil ijtihad para sahabat, yaitu : Umar bin Khattab RA tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada seseorang yang mencuri karena kelaparan (darurat/terpaksa). Dan Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa wanita yang suaminya meninggal dunia dan belum dicampuri serta belum ditentukan maharnya, hanya berhak mendapatkan mut'ah. Ali menyamakan kedudukan wanita tersebut dengan wanita yang telah dicerai oleh suaminya dan belum dicampuri serta belum ditentukan maharnya, yang oleh syara' ditetapkan hak mut'ah baginya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:
Artinya: "Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu memberikan mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (Al-Baqarah : 236).
Dari contoh-contoh ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, demikian pula oleh para sahabatnya baik di kala Rasulullah SAW masih hidup atau setelah beliau wafat, tampak adanya cara-cara yang digunakannya, sekalipun tidak dikemukakan dan tidak disusun kaidah-kaidah (aturan-aturan)nya; sebagaimana yang kita kenal dalam Ilmu Ushul Fiqh; karena pada masa Rasulullah SAW, demikian pula pada masa sahabatnya, tidak dibutuhkan adanya kaidah-kaidah dalam berijtihad dengan kata lain pada masa Rasulullah SAW dan pada masa sahabat telah terjadi praktek berijtihad, hanya saja pada waktu-waktu itu tidak disusun sebagai suatu ilmu yang kelak disebut dengan Ilmu Ushul Fiqh karena pada waktu-waktu itu tidak dibutuhkan adanya.
Yang demikian itu, karena Rasulullah SAW mengetahui cara-cara nash dalam menunjukkan hukum baik secara langsung atau tidak langsung, sehingga beliau tidak membutuhkan adanya kaidah-kaidah dalam berijtihad, karena mereka mengetahui sebab-sebab turun (asbabun nuzul) ayat-ayat Al-Qur'an, sebab-sebab datang (asbabul wurud) Al-Hadits, mempunyai ketajaman dalam memahami rahasia-rahasia, tujuan dan dasar-dasar syara' dalam menetapkan hukum yang mereka peroleh karena mereka mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap bahasa mereka sendiri (Arab) yang juga bahasa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan pengetahuan yang mereka miliki itu, mereka mampu berijtihad tanpa membutuhkan adanya kaidah-kaidah. Pada masa tabi'in, tabi'it-tabi'in dan para imam mujtahid, di sekitar abad II dan III Hijriyah wilayah kekuasaan Islam telah menjadi semakin luas, sampai ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan bangsa Arab atau tidak berbahasa Arab dan beragam pula situasi dan kondisinya serta adat istiadatnya. Banyak diantara para ulama yang bertebaran di daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit penduduk daerah-daerah itu yang memeluk agama Islam. Dengan semakin tersebarnya agama Islam di kalangan penduduk dari berbagai daerah tersebut, menjadikan semakin banyak persoalan-persoalan hukum yang timbul. Yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Yang demikian itu, karena Rasulullah SAW mengetahui cara-cara nash dalam menunjukkan hukum baik secara langsung atau tidak langsung, sehingga beliau tidak membutuhkan adanya kaidah-kaidah dalam berijtihad, karena mereka mengetahui sebab-sebab turun (asbabun nuzul) ayat-ayat Al-Qur'an, sebab-sebab datang (asbabul wurud) Al-Hadits, mempunyai ketajaman dalam memahami rahasia-rahasia, tujuan dan dasar-dasar syara' dalam menetapkan hukum yang mereka peroleh karena mereka mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap bahasa mereka sendiri (Arab) yang juga bahasa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan pengetahuan yang mereka miliki itu, mereka mampu berijtihad tanpa membutuhkan adanya kaidah-kaidah. Pada masa tabi'in, tabi'it-tabi'in dan para imam mujtahid, di sekitar abad II dan III Hijriyah wilayah kekuasaan Islam telah menjadi semakin luas, sampai ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan bangsa Arab atau tidak berbahasa Arab dan beragam pula situasi dan kondisinya serta adat istiadatnya. Banyak diantara para ulama yang bertebaran di daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit penduduk daerah-daerah itu yang memeluk agama Islam. Dengan semakin tersebarnya agama Islam di kalangan penduduk dari berbagai daerah tersebut, menjadikan semakin banyak persoalan-persoalan hukum yang timbul. Yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Untuk itu para ulama yang tinggal di berbagai daerah itu berijtihad mencari ketetapan hukumnya. Karena banyaknya persoalan-persoalan hukum yang timbul dan karena pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang yang berkembang dengan pesat yang terjadi pada masa ini, kegiatan ijtihad juga mencapai kemajuan yang besar dan lebih bersemarak. Dalam pada itu, pada masa ini juga semakin banyak terjadi perbedaan dan perdebatan antara para ulama mengenai hasil ijtihad, dalil dan jalan-jalan yang ditempuhnya. Perbedaan dan perdebatan tersebut, bukan saja antara ulama satu daerah dengan daerah yang lain, tetapi juga antara para ulama yang sama-sama tinggal dalam satu daerah.
Kenyataan-kenyataan di atas mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah syari'ah yakni kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syara' dalam menetapkan hukum dalam berijtihad. Demikian pula dengan semakin luasnya daerah kekuasan Islam dan banyaknya penduduk yang bukan bangsa Arab memeluk agama Islam. Maka terjadilah pergaulan antara orang-orang Arab dengan mereka. Dari pergaulan antara orang-orang Arab dengan mereka itu membawa akibat terjadinya penyusupan bahasa-bahasa mereka ke dalam bahasa Arab, baik berupa ejaan, kata-kata maupun dalam susunan kalimat, baik dalam ucapan maupun dalam tulisan. Keadaan yang demikian itu, tidak sedikit menimbulkan keraguan dan kemungkinan-kemungkinan dalam memahami nash-nash syara'. Hal ini mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah lughawiyah (bahasa), agar dapat memahami nash-nash syara' sebagaimana dipahami oleh orang-orang Arab sewaktu turun atau datangnya nash-nash tersebut. Dengan disusunnya kaidah-kaidah syar'iyah dan kaidah-kaidah lughawiyah dalam berijtihad pada abad II Hijriyah, maka telah terwujudlah Ilmu Ushul Fiqh.
Dikatakan oleh Ibnu Nadim bahwa ulama yang pertama kali menyusun kitab Ilmu Ushul Fiqh ialah Imam Abu Yusuf - murid Imam Abu Hanifah - akan tetapi kitab tersebut tidak sampai kepada kita. Diterangkan oleh Abdul Wahhab Khallaf, bahwa ulama yang pertama kali membukukan kaidah-kaidah Ilmu Ushul Fiqh dengan disertai alasan-alasannya adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'iy (150-204 H) dalam sebuah kitab yang diberi nama Ar-Risalah. Dan kitab tersebut adalah kitab dalam bidang Ilmu Ushul Fiqh yang pertama sampai kepada kita. Oleh karena itu terkenal di kalangan para ulama, bahwa beliau adalah pencipta Ilmu Ushul Fiqh.
BAB-V
KESALAHPAHAMAN TERHADAP HUKUM ISLAM
KESALAHPAHAMAN TERHADAP HUKUM ISLAM
1. Cakupan Hukum Islam
Sejauh ini masih banyak kalangan yang memahami bahwa hukum Islam hanyalah meliputi hal-hal yang sering disebut sebagai “hukum”, yang mencakup pidana dan perdata. Pemahaman ini perlu diluruskan. Sebab hukum Islam tidaklah sesempit itu. Hukum Islam, bahkan, bisa dikatakan meliputi segenap aspek kehidupan, sampai kepada hal-hal yang seringkali tidak dikategorikan dalam wilayah “hukum”. Sebagai contoh, perkara-perkara yang sangat privat dan tidak mempunyai dimensi sosial sekalipun, ternyata masuk dalam cakupan hukum Islam, yang mana perkara-perkara yang demikian ini tidak pernah dianggap oleh hukum Barat sebagai permasalahan hukum. Keluasan cakupan hukum Islam sebetulnya tidaklah aneh karena secara teologis berawal dari konsep keparipurnaan Islam (syumuliyyat al-Islam). Konsep ini mengatakan bahwasanya Islam bersifat paripurna, yang berarti telah mengatur seluruh aspek kehidupan tanpa kecuali. Dalam pandangan Islam, seluruh permasalahan manusia mesti ada hukumnya. Tidak ada satupun persoalan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh Islam. Salah satu hal yang mendukung paham ini adalah adanya prinsip kontinuitas (al-istishhab) dalam metodologi hukum Islam. Kalangan fuqaha’ (ahli hukum Islam) seringkali menggambarkan cakupan hukum Islam dengan cara mengklasifikasikan hukum Islam atas masalah-masalah ta’abbudiyah, muamalah, ahwal al-syakhshiyyat, jinayat (pidana), dan siyasat (politik).
Klasifikasi ini memang cukup representatif, namun belumlah benar-benar mencakup keseluruhan aspek yang diatur oleh hukum Islam. Namun, dengan berpegang pada klasifikasi tersebut pun, kita sudah bisa menggambarkan perbedaan cakupan antara hukum Islam dan hukum Barat (yang mana cakupan hukum Islam lebih luas). Aspek muamalah dan ahwal al-syakhshiyyat barangkali identik dengan aspek perdata dalam terminologi hukum Barat. Yang aneh adalah masuknya aspek ibadah dan siyasat dalam cakupan hukum Islam. Aspek ibadah kebanyakan bersifat transendental, privat, dan tidak berdimensi sosial. Aspek ini lebih berorientasi pada hubungan antara manusia dan Tuhan sehingga menurut hukum Barat bukanlah merupakan permasalahan hukum.
Namun anehnya, Islam menganggapnya sebagai permasalahan hukum. Bahkan, sementara kalangan sering mengkonotasikan fiqih Islam (istilah lain bagi hukum Islam) sebagai aspek ibadah. Tatkala mereka menentang berlarut-larutnya diskursus dalam masalah-masalah ibadah maka mereka berkata,”Jangan hanya berkutat pada fiqih saja!” Masuknya siyasat (politik) dalam cakupan hukum Islam juga merupakan keanehan tersendiri. Dalam khazanah keilmuan Barat (maksudnya, yang tumbuh secara formatif di Barat), politik terpisah dari hukum sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri. Sebetulnya yang patut menjadi perhatian bukanlah pemisahan itu sendiri, akan tetapi implikasinya. Pemisahan tersebut ternyata telah memposisikan keduanya secara berseberangan atau bahkan berhadap-hadapan. Pemikiran-pemikiran politik dan hukum atas satu permasalahan yang sama terkadang amat berbeda bahkan bertentangan. Karena itu tidaklah mengherankan apabila ada orang yang berkata,”Permasalahan ini jika diselesaikan secara yuridis adalah begini sementara jika diselesaikan secara politis adalah begitu!” Karena itu pula amat wajar apabila kemudian muncul semacam pertentangan klan antara para politisi dan para yuris.
Namun anehnya, Islam menganggapnya sebagai permasalahan hukum. Bahkan, sementara kalangan sering mengkonotasikan fiqih Islam (istilah lain bagi hukum Islam) sebagai aspek ibadah. Tatkala mereka menentang berlarut-larutnya diskursus dalam masalah-masalah ibadah maka mereka berkata,”Jangan hanya berkutat pada fiqih saja!” Masuknya siyasat (politik) dalam cakupan hukum Islam juga merupakan keanehan tersendiri. Dalam khazanah keilmuan Barat (maksudnya, yang tumbuh secara formatif di Barat), politik terpisah dari hukum sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri. Sebetulnya yang patut menjadi perhatian bukanlah pemisahan itu sendiri, akan tetapi implikasinya. Pemisahan tersebut ternyata telah memposisikan keduanya secara berseberangan atau bahkan berhadap-hadapan. Pemikiran-pemikiran politik dan hukum atas satu permasalahan yang sama terkadang amat berbeda bahkan bertentangan. Karena itu tidaklah mengherankan apabila ada orang yang berkata,”Permasalahan ini jika diselesaikan secara yuridis adalah begini sementara jika diselesaikan secara politis adalah begitu!” Karena itu pula amat wajar apabila kemudian muncul semacam pertentangan klan antara para politisi dan para yuris.
Umat Islam hendaknya tidak secara latah mengikuti arus pertentangan ini. Dalam Islam, politik dan hukum itu identik (atau kalau kita mengikuti klasifikasi yang baru lalu maka politik merupakan bagian dari hukum). Dalam Islam tidak layak timbul pertentangan antara pemikiran politik dan pemikiran hukum, karena memang sejak awal tidak ada alasan untuk itu. Hukum Islam memiliki suatu pola pikir yang amat komprehensif. Ushul fiqih (sebagian orang menyebutnya sebagai filsafat hukum Islam) misalnya, telah meletakkan suatu pola pikir yang amat mendasar, yang digali secara radikal dari Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Oleh karena sifatnya yang mendasar dan filosofis itulah maka konsep-konsep ushul fiqih bisa “ditarik” secara induktif kemanapun juga. Konsep-konsep ushul fiqih bisa digunakan sebagai basis pemikiran bagi segenap persoalan manusia, termasuk persoalan politik. Sehingga, tatkala kita berbicara tentang politik maka pada dasarnya kita juga berbicara tentang hukum. Karena itu, dalam “kamus” Islam tidak ada “istilah” pertentangan antara politik dan hukum. Kesatuan antara politik dan hukum dalam Islam memang seringkali terlupakan sehingga memunculkan berbagai polemik yang sebetulnya tidak perlu ada.
2. Perbedaan antara Syariat dan Fiqih
Sebagian (kalau bukan kebanyakan) orang menganggap bahwa syariat dan fiqih adalah sama. Padahal, keduanya berbeda dari segi bahwa syariat berorientasi Ilahiyah sementara fiqih berorientasi pada pemikiran manusia. Maksudnya, syariat merupakan ketentuan-ketentuan kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah sementara fiqih (yang secara lughawi bermakna pemahaman) merupakan interpretasi manusia atas ketentuan-ketentuan tersebut. Mengapa perlu ada interpretasi? Jawabnya adalah karena manusia dituntut untuk bisa memahami ketentuan-ketentuan Allah tersebut, yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Dengan apa manusia akan memahaminya? Jawabnya, tentu dengan akal. Tanpa akal, manusia tidak akan dapat memahami Al-Qur’an dan Al-Sunnah.
Karena itu apabila ada yang mengatakan bahwa akal lebih tinggi daripada wahyu maka jangan terburu-buru menyalahkannya. Perkataan tersebut benar apabila yang dimaksudkan adalah bahwa wahyu tidak akan berarti sedikit pun tanpa adanya akal sebagai alat untuk memahami. Namun apabila perkataan tersebut dimaksudkan dengan makna tingkatan otoritas maka itulah sebatil-batil perkataan! Karena fiqih merupakan hasil pemikiran manusia maka kebenarannya bersifat relatif. Sebaliknya, kebenaran syariat bersifat absolut karena merupakan ketetapan Allah Yang Maha Benar. Sebetulnya, kebenaran dalam setiap persoalan hanya ada satu yaitu sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat. Akan tetapi karena syariat itu hanya bisa dipahami melalui fiqih, sementara fiqih merupakan hasil pemikiran manusia yang bisa berbeda antara satu orang dan orang lain, maka kebenaran itupun muncul sebagai lebih dari satu. Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi yang mengatakan bahwa hasil ijtihad secara hakiki bisa benar dan bisa salah, namun kedua-keduanya tetaplah “benar” (ditunjukkan dengan pemberian pahala) sepanjang diperoleh melalui metode ijtihad yang benar. Oleh karena itu, adanya berbagai perbedaan pendapat dalam fiqih (sepanjang dihasilkan melalui metode ijtihad yang benar) merupakan suatu kewajaran. Kita harus menyadari bahwa hasil pemikiran manusia bisa berbeda-beda meskipun mengenai masalah yang sama, yang secara hakiki hanya mempunyai satu jawaban yang benar.
Hal lain yang juga patut dicatat dalam masalah relativitas kebenaran fiqih adalah bahwasanya ada ketentuan-ketentuan syariat yang dinyatakan secara qath’iy al-dalalah dan ada pula yang dinyatakan secara zhanniy al-dalalah. Dalam hal-hal yang qath’iy, setiap akal sehat (common sense, al-‘aql al-dharuriy) pasti akan memahaminya secara sama. Namun dalam hal-hal yang zhanniy, manusia mungkin akan memahaminya secara berbeda-beda, meskipun secara hakiki pemahaman yang diharapkan hanyalah satu.
3. Pergeseran Makna pada Kata Syariat dan Fiqh
Selanjutnya, kita akan melakukan tinjauan bahasa terhadap kata syariat dan fiqih. Kedua kata ini dalam perkembangannya telah mengalami penyempitan makna, sehingga akhirnya makna populernya sudah bergeser (menyempit) dari makna aslinya. Dalam penggunaan populer, istilah syariat sering diartikan sebagai hukum Islam yang berkonotasi pada aspek legal formal dalam Islam. Istilah ini sering disandingkan bersama-sama dengan akidah dan akhlaq, dalam trio bangunan Islam: akidah-syariat-akhlaq (dalam istilah lain: iman - amal (islam) - ihsan). Di sini syariat dibedakan dari akidah dan akhlaq (etika). Padahal, jika merujuk pada makna aslinya maka syariat juga meliputi akidah dan akhlaq. Mengapa demikian? Jawabnya adalah karena makna asli syariat adalah sistem aturan kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah (secara lughawi, syariat bermakna jalan yang lebar), yang tentu saja meliputi segenap aspek kehidupan, termasuk akidah dan akhlaq. Jadi, dalam makna aslinya, syariat kurang lebih semakna dengan al-din atau al-millat (agama). Demikian pula, istilah fiqih juga telah mengalami pergeseran (penyempitan) makna. Dalam penggunaan populer, fiqih diartikan sebagai ilmu hukum Islam, atau lebih tepatnya ilmu yang mempelajari ketentuan-ketentuan syariat yang bersifat amaliyah dengan didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci.
Pendek kata, secara populer fiqih merupakan suatu disiplin ilmu. Padahal apabila kita merujuk pada makna aslinya, maka fiqih sebetulnya bermakna pemahaman yang mendalam. Karena itu, istilah tafaqquh fi al-din harus diartikan sebagai usaha memahami agama secara mendalam dalam seluruh aspeknya, tidak hanya aspek hukumnya - par excellence - saja. Pengetahuan tentang pergeseran makna kata amatlah penting karena kata-kata tersebut seringkali merupakan kosakata yang digunakan dalam Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Dalam hal ini, kita tidak boleh terjebak kedalam pemahaman yang didasarkan pada pemaknaan yang telah bergeser. Sebaliknya, kita harus tetap memandang kata-kata tersebut secara orisinil dengan tetap memperhatikan konteksnya. Pergeseran makna yang absah dalam kerangka memahami Al-Qur’an dan Al-Sunnah hanyalah pergeseran makna yang terjadi pada saat kedua sumber hukum itu masih dalam proses pembentukannya (misalnya kata shalat yang telah menyempit dari makna doa kepada makna suatu bentuk aktivitas ritual, dimana penyempitan makna ini terjadi saat Al-Qur’an masih turun).
4. Hukum Pidana Islam dan Penerapannya
Sebagai bagian akhir dari tulisan ini, penulis ingin meluruskan adanya berbagai kesalahpahaman terhadap pemberlakuan hukum pidana Islam (jinayat) - yang meliputi qishash, hudud, ta’zir, dan kaffarah. Memang patut disayangkan bahwa ternyata sebagian besar umat Islam ternyata masih mengidap phobia terhadap hukum pidana Islam, bahkan hukum Islam secara umum. Mereka yang mengidap phobia ini bisa dibedakan menjadi beberapa kelompok. Pertama, orang-orang non muslim yang memiliki antipati terhadap Islam sehingga selalu berusaha menghalangi tegaknya hukum Islam (terutama yang mempunyai dimensi sosial dan politik). Dalam usahanya, mereka tidak segan-segan mempelajari Islam dengan tekun untuk mencari titik-titik kelemahannya untuk kemudian menjadikannya sebagai senjata untuk menyerang Islam.
Dari sinilah kemudian muncul orientalisme (yang dalam perkembangannya lebih terfokus pada Islamo-orientalisme atau orientalisme Semitik) – meskipun dalam perkembangannya muncul pula studi-studi orientalisme dengan tujuan-tuuan yang lebih ilmiah dan obyektif. Golongan pertama ini senantiasa berusaha menyebarkan bias (syubhat) tentang hukum Islam ke tengah-tengah kaum muslimin, dengan dukungan media informasi dan komunikasi yang unggul. Kedua, orang-orang yang menolak penerapan hukum Islam karena akan merugikan kepentingan-kepentingan pribadinya. Golongan kedua ini bisa berasal dari muslim maupun non muslim. Ketiga, orang-orang yang menolak hukum Islam karena belum memahaminya secara benar. Agaknya, persentase golongan ketiga ini cukup besar dalam tubuh umat Islam, meskipun golongan ini juga terdapat pada sebagian non muslim. Yang patut dicamkan, ternyata kebelumpahaman golongan ini ternyata sangat diperburuk oleh gencarnya syubhat yang dilancarkan oleh golongan pertama (dan mungkin juga golongan kedua). Kali ini, penulis ingin memfokuskan diri pada golongan ketiga (terakhir).
Tugas besar para juru dakwah (terutama para fuqaha’ par excellence) adalah menanamkan pemahaman yang benar tentang hukum Islam kepada golongan terakhir ini, yang sebagian besar adalah umat Islam sendiri. Dalam masalah penerapan hukum pidana Islam misalnya, kebanyakan orang mengira bahwa hukum pidana Islam amatlah kejam dan tidak berperikemanusiaan. Mereka mengira bahwa hukuman berat akan dengan mudah dijatuhkan. Mereka hanya tahu bahwa setiap pembunuh akan dibunuh pula. Padahal pembunuhan sendiri mempunyai beberapa kategori, yaitu ‘amd (sengaja) dan khatha’(tidak sengaja) – Imam Syafi’i menambahkan satu kategori lagi yang merupakan pertengahan diantara keduanya, yang disebut syibh ‘amd (mirip sengaja). Masing-masing kategori memiliki bentuk hukumannya sendiri-sendiri, yang tidak hanya berupa balas bunuh (qawad). Pendapat yang populer bahkan mengatakan bahwa untuk kategori ‘amd dan syibh ‘amd, hukuman bisa saja hanya berupa denda (diyat) apabila ahli waris korban menghendakinya. Khusus untuk kategori khatha’, hukumannya hanyalah berupa denda. Lagipula, bukankah pantas dan adil bahwa seorang pembunuh harus dibunuh pula?
Pengalaman kehidupan mencatat bahwa angka pembunuhan terus meningkat akibat hukum yang tidak tegas dan berwibawa. Perlu dipahami, syariat Islam (al-Muhammadiyyat) merupakan syariat yang adil dan pertengahan (wasath). Ibn Taimiyyah – dan diikuti oleh Muhammad Abduh - mengatakan bahwa syariat Muhammad merupakan pertengahan antara syariat Musa yang tegas serta keras dan syariat Isa yang penuh kasih-sayang dan kelembutan. Dalam hal hudud, kebanyakan orang mengira bahwa hadd akan sangat mudah dijatuhkan. Padahal sebetulnya tidaklah demikian. Hadd zina, sebagai contoh, baru bisa dijatuhkan apabila memenuhi hal-hal berikut: 1. Pelaku mengakui sendiri perbuatannya (al-iqraar) yang berakibat dirinya di-hadd, namun penuduhan zina terhadap orang lain (misalnya terhadap pasangan zinanya sekalipun) tidak bisa menyebabkan tertuduh di-hadd. Bahkan apabila tuduhan itu bukan antara suami isteri dan tidak disertai saksi yang cukup maka penuduh diancam dengan hadd qadzf (tuduhan palsu). Sedangkan apabila penuduhan itu terjadi antara suami isteri maka timbullah li’aan (saling melaknat). 2. Apabila tidak ada pengakuan (al-iqraar), maka hadd hanya bisa jatuh apabila ada persaksian dari empat orang saksi laki-laki yang adil, yang mana saksi-saksi tersebut harus melihat sendiri bahwa hasyafah telah masuk kedalam farj, dan semua saksi harus menyatakan bahwa zina tersebut terjadi pada tempat dan waktu yang sama. 3. Tidak ada syubhat, baik syubhat bi al-fa’il, syubhat bi al-fi’l, atupun syubhat fi al-hukm.
Hal lain dalam hukum pidana Islam yang harus dipahami adalah bahwasanya penegakan atau pemberlakuan bentuk-bentuk hukum pidana Islam hanya bisa dilakukan apabila “infrastrukturnya” telah siap. Hukum zina tidak bisa diterapkan pada suatu masyarakat yang masih dipenuhi dengan berbagai bentuk pornografi dan tempat-tempat mesum yang menjamur. Jika tidak, alangkah banyaknya orang yang akan dicambuk dan dirajam setiap harinya! Hukum potong tangan belum boleh diterapkan pada suatu masyarakat yang sedang dilanda bencana kelaparan atau penuh dengan monopoli dan kesenjangan sosial yang fatal. Kalau tidak, alangkah banyaknya tangan-tangan yang akan dipotong setiap harinya! Hukuman hadd bagi peminum khamr belum boleh diberlakukan apabila pabrik-pabrik khamr masih dibiarkan leluasa memproduksi khamr-nya. Sebetulnya masih banyak permasalahan mengenai hukum Islam dan penerapannya, yang harus dipahamkan secara benar kepada umat Islam, dan umat manusia pada umumnya. Usaha-usaha penerangan ini harus dilakukan dengan baik dan tekun, dengan memanfaatkan berbagai sarana informasi dan komunikasi di jaman modern ini.
Hal lain dalam hukum pidana Islam yang harus dipahami adalah bahwasanya penegakan atau pemberlakuan bentuk-bentuk hukum pidana Islam hanya bisa dilakukan apabila “infrastrukturnya” telah siap. Hukum zina tidak bisa diterapkan pada suatu masyarakat yang masih dipenuhi dengan berbagai bentuk pornografi dan tempat-tempat mesum yang menjamur. Jika tidak, alangkah banyaknya orang yang akan dicambuk dan dirajam setiap harinya! Hukum potong tangan belum boleh diterapkan pada suatu masyarakat yang sedang dilanda bencana kelaparan atau penuh dengan monopoli dan kesenjangan sosial yang fatal. Kalau tidak, alangkah banyaknya tangan-tangan yang akan dipotong setiap harinya! Hukuman hadd bagi peminum khamr belum boleh diberlakukan apabila pabrik-pabrik khamr masih dibiarkan leluasa memproduksi khamr-nya. Sebetulnya masih banyak permasalahan mengenai hukum Islam dan penerapannya, yang harus dipahamkan secara benar kepada umat Islam, dan umat manusia pada umumnya. Usaha-usaha penerangan ini harus dilakukan dengan baik dan tekun, dengan memanfaatkan berbagai sarana informasi dan komunikasi di jaman modern ini.
BAB-VI
ALIRAN-ALIRAN DALAM ILMU USHUL FIQH
ALIRAN-ALIRAN DALAM ILMU USHUL FIQH
Perbedaan pendapat yang sering terjadi diantara para ulama dalam hal penetapan istilah untuk suatu pengertian penting. Dalam membahas Ilmu Ushul Fiqh, para ulama tidak selalu sepakat dalam menetapkan istilah-istilah untuk suatu pengertian dan dalam menetapkan jalan-jalan yang ditempuh dalam pembahasannya. Dalam hal ini mereka terbagi menjadi dua aliran, yaitu Aliran Mutakallimin dan Aliran Hanafiyah.
1. Aliran Mutakallimin Para ulama dalam aliran ini dalam pembahasannya dengan menggunakan cara-cara yang digunakan dalam ilmu kalam yakni menetapkan kaidah ditopang dengan alasan-alasan yang kuat baik naqliy (dengan nash) maupun 'aqliy (dengan akal fikiran) tanpa terikat dengan hukum furu' yang telah ada dari madzhab manapun, sesuai atau tidak sesuai kaidah dengan hukum-hukum furu' tersebut tidak menjadi persoalan. Aliran ini diikuti oleh para ulama dari golongan Mu'tazilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Di antara kitab-kitab Ilmu Ushul Fiqh dalam aliran ini, yaitu:
- Kitab Al-Mu'tamad disusun oleh Abdul Husain Muhammad bin Aliy al-Bashriy al-Mu'taziliy asy-Syafi'iy (wafat pada tahun 463 Hijriyah).
- Kitab Al-Burhan disusun oleh Abdul Ma'aliy Abdul Malik bin Abdullah al-Jawainiy an-Naisaburiy asy-Syafi'iy yang terkenal dengan nama Imam Al-Huramain ( wafat pada tahun 487 Hijriyah).
- Kitab AI Mushtashfa disusun oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazaliy Asy Syafi ' iy (wafat pada tahun 505 Hijriyah).
Dari tiga kitab tersebut yang dapat ditemui hanyalah kitab Al Musht.shfa, sedangkan dua kitab lainnya hanya dapat dijumpai nukilan-nukilannya dalam kitab yang disusun oleh para ulama berikut, seperti nukilan kitab dari Al Burhan oleh Al Asnawiy dalam kitab Syahrul Minhaj.
Kitab-kitab yang datang berikutnya yakni kitab Al Mahshul disusun oleh Fakhruddin Muhammad bin Umar Ar Raziy Asy Syafi'iy (wafat pada tahun 606 Hijriyah). Kitab ini merupakan ringkasan dari tiga kitab yang disebutkan di atas. Kemudian kitab Al Mahshul ini diringkas lagi oleh dua orang yaitu:
Kitab-kitab yang datang berikutnya yakni kitab Al Mahshul disusun oleh Fakhruddin Muhammad bin Umar Ar Raziy Asy Syafi'iy (wafat pada tahun 606 Hijriyah). Kitab ini merupakan ringkasan dari tiga kitab yang disebutkan di atas. Kemudian kitab Al Mahshul ini diringkas lagi oleh dua orang yaitu:
- Tajjuddin Muhammad bin Hasan Al Armawiy (wafat pada tahun 656 Hijriyah) dalam kitabnya yang diberi nama Al Hashil.
- Mahmud bin Abu Bakar Al Armawiy (wafat pada tahun 672 Hijriyah) dalam kitabnya yang berjudul At Tahshil.
Kemudian Al Qadliy Abdullah bin Umar Al Badlawiy (wafat pada tahun 675 Hijriyah) menyusun kitab Minhajul Wushul Ila 'Ilmil Ushul yang isinya disarikan dari kitab At Tahshil. Akan tetapi karena terlalu ringkasnya isi kitab tersebut, maka sulit untuk dapat dipahami. Hal ini mendorong para ulama berikutnya untuk menjelaskannya. Di antara mereka yaitu Abdur Rahim bin Hasan AJ Asnawiy Asy Syafi'iy (wafat pada tahun 772 Hjjriyah) dengan menyusun sebuah kitab yang menjelaskan isi kitab Minhajul Wushu Ila 'Ilmil Ushul tersebut. Selain kitab Al Mashul yang merupakan ringkasan dari kitab-kitab Al Mu tamad, Al Burhan dan Al Mushtashfa, masih ada kitab yang juga merupakan ringkasan dari tiga kitab tersebut, yaitu kitab Al Ihkam fi Ushulil Ahkam, disusun oleh Abdul Hasan Aliy yang terkenal dengan nama Saifuddin Al Amidiy Asy Syafi'iy (wafat pada tahun 631 Hijriyah).
Kitab Al Ihkam fi Ushulil Ahkam ini kemudian diringkas oleh Abu Amr Utsman bin Umar yang terkenal dengan nama Ibnul Hajib Al Malikiy (wafat pada tahun 646 Hijriyah) dalam kitabnya yang diberi nama Muntahal Su 'li wal Amal fi Ilmil Ushul wal Jidal. Kemudian kitab itu beliau ringkas lagi dalam sebuah kitab, dengan nama Mukhtasharul Muntaha. Kitab ini mirip dengan kitab Minhajul Wulshul ila Ilmil Ushul, sulit difahami karena ringkasnya. Hal ini mengundang minat para ulama berikutnya untuk menjelaskannya. Di antara mereka ialah ' AdldIuddin 'Abdur Rahman bin Ahmad Al Ajjiy (wafat tahun 756 Hijriyah) dengan menyusun sebuah kitab yang menjelaskan kitab Mukhtasharul Muntaha tersebut.
2. Aliran Hanafiyah. Para ulama dalam aliran ini, dalam pembahasannya, berangkat dari hukum-hukum furu' yang diterima dari imam-imam (madzhab) mereka; yakni dalam menetapkan kaidah selalu berdasarkan kepada hukum-hukum furu ' yang diterima dari imam-imam mereka. Jika terdapat kaidah yang bertentangan dengan hukum-hukum furu' yang diterima dari imam-imam mereka, maka kaidah itu diubah sedemikian rupa dan disesuaikan dengan hukum-hukum furu' tersebut. Jadi para ulama dalam aliran ini selalu menjaga persesuaian antara kaidah dengan hukum furu' yang diterima dari imam-imam mereka.
Di antara kitab-kitab Ilmu Ushul Fiqh dalam aliran ini, yaitu: kitab yang disusun oleh Abu Bakar Ahmad bin' Aliy yang terkenal dengan sebutan Al Jashshash (wafat pada tahun 380 Hijriyah), kitab yang disusun oleh Abu Zaid ' Ubaidillah bin 'Umar Al Qadliy Ad Dabusiy (wafat pada tahun 430 Hijriyah), kitab yang disusun oleh Syamsul Aimmah Muhammad bin Ahmad As Sarkhasiy (wafat pada tahun 483 Hijriyah). Kitab yang disebut terakhir ini diberi penjelasan oleh Alauddin Abdul 'Aziz bin Ahmad Al Bukhariy (wafat pada tahun 730 Hijriyah) dalam kitabnya yang diberi nama Kasyful Asrar .Dan juga kitab Ilmu Ushul Fiqh dalam aliran ini ialah kitab yang disusun oleh Hafidhuddin 'Abdullah bin Ahmad An Nasafiy (wafat pada tahun 790 Hijriyah) yang berjudul 'Al Manar, dan syarahnya yang terbaik yaitu Misykatul Anwar. Dalam abad itu muncul para ulama yang dalam pembahasannya memadukan antara dua aliran tersebut di atas, yakni dalam menetapkan kaidah, memperhatikan alasan-alasannya yang kuat dan memperhatikan pula persesuaiannya dengan hukum-hukum furu'. Di antara mereka itu ialah: Mudhafaruddin Ahmad bin 'Aliy As Sya'atiy Al Baghdadiy (wafat pada tahun 694 Hijriyah) dengan menulis kitab Badi'un Nidham yang merupakan paduan kitab yang disusun oleh Al Bazdawiy dengan kitab Al Ihkam fi Ushulil Ahkam yang ditulis oleh Al Amidiy; dan Syadrusiy Syari'ah 'Ubaidillah bin Mas'ud Al Bukhariy Al Hanafiy (wafat pada tahun 747 Hijriyah) menyusun kitab Tanqihul Ushul yang kemudian diberikan penjelasan-penjelasan dalam kitabnya yang berjudul At Taudlih .
Kitab tersebut merupakan ringkasan kitab yang disusun oleh Al Bazdawiy, kitab AI Mahshul oleh Ar Raziy dan kitab Mukhtasharul Muntaha oleh Ibnul Hajib. Demikian pula termasuk ulama yang memadukan dua aliran tersebut di atas, yaitu Tajuddin 'Abdul Wahhab bin' Aliy As Subkiy Asy Syafi'iy (wafat pada tahun 771 Hijriyah) dengan menyusun kitab Jam'ul Jawami' dan Kamaluddin Muhammad 'Abdul Wahid yang terkenal dengan Ibnul Humam (wafat pada tahun 861 Hijriyah) dengan menyusun kitab yang diberi nama At Tahrir.
Dalam kaitan dengan pembahasan Ilmu Ushul Fiqh ini, perlu dikemukakan bahwa Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy Syatibiy (wafat pada tahun 760 Hijriyah) telah menyusun sebuah kitab Ilmu Ushul Fiqh, yang diberi nama Al Muwafaqat. Dalam kitab tersebut selain dibahas kaidah-kaidah juga dibahas tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Kemudian perlu pula diketahui kitab-kitab Ilmu Ushul Fiqh yang disusun oleh para ulama pada masa belakangan ini, antara lain: kitab Irsyadul Fuhul i/a Tahqiqi/ Haq min 'I/mil Ushu/ oleh Imam Muhammad bin' Aliy Asy Syaukaniy (wafat pada tahun 1255 Hijriyah), kitab Tashilu/ Wushu/ i/a 'Ilmi/ Ushu/ oleh Syaikh Muhammad 'Abdur Rahman Al Mihlawiy (wafat pada tahun 1920 Hijriyah); kitab Ushu/u/ Fiqh oleh Syaikh Muhammad Al Khudlariy Bak (wafat pada tahun 1345 Hijriyah/ 1927 Masehi) dan kitab-kitab Ilmu Ushul Fiqh yang lain.
Di antara kitab-kitab Ilmu Ushul Fiqh dalam aliran ini, yaitu: kitab yang disusun oleh Abu Bakar Ahmad bin' Aliy yang terkenal dengan sebutan Al Jashshash (wafat pada tahun 380 Hijriyah), kitab yang disusun oleh Abu Zaid ' Ubaidillah bin 'Umar Al Qadliy Ad Dabusiy (wafat pada tahun 430 Hijriyah), kitab yang disusun oleh Syamsul Aimmah Muhammad bin Ahmad As Sarkhasiy (wafat pada tahun 483 Hijriyah). Kitab yang disebut terakhir ini diberi penjelasan oleh Alauddin Abdul 'Aziz bin Ahmad Al Bukhariy (wafat pada tahun 730 Hijriyah) dalam kitabnya yang diberi nama Kasyful Asrar .Dan juga kitab Ilmu Ushul Fiqh dalam aliran ini ialah kitab yang disusun oleh Hafidhuddin 'Abdullah bin Ahmad An Nasafiy (wafat pada tahun 790 Hijriyah) yang berjudul 'Al Manar, dan syarahnya yang terbaik yaitu Misykatul Anwar. Dalam abad itu muncul para ulama yang dalam pembahasannya memadukan antara dua aliran tersebut di atas, yakni dalam menetapkan kaidah, memperhatikan alasan-alasannya yang kuat dan memperhatikan pula persesuaiannya dengan hukum-hukum furu'. Di antara mereka itu ialah: Mudhafaruddin Ahmad bin 'Aliy As Sya'atiy Al Baghdadiy (wafat pada tahun 694 Hijriyah) dengan menulis kitab Badi'un Nidham yang merupakan paduan kitab yang disusun oleh Al Bazdawiy dengan kitab Al Ihkam fi Ushulil Ahkam yang ditulis oleh Al Amidiy; dan Syadrusiy Syari'ah 'Ubaidillah bin Mas'ud Al Bukhariy Al Hanafiy (wafat pada tahun 747 Hijriyah) menyusun kitab Tanqihul Ushul yang kemudian diberikan penjelasan-penjelasan dalam kitabnya yang berjudul At Taudlih .
Kitab tersebut merupakan ringkasan kitab yang disusun oleh Al Bazdawiy, kitab AI Mahshul oleh Ar Raziy dan kitab Mukhtasharul Muntaha oleh Ibnul Hajib. Demikian pula termasuk ulama yang memadukan dua aliran tersebut di atas, yaitu Tajuddin 'Abdul Wahhab bin' Aliy As Subkiy Asy Syafi'iy (wafat pada tahun 771 Hijriyah) dengan menyusun kitab Jam'ul Jawami' dan Kamaluddin Muhammad 'Abdul Wahid yang terkenal dengan Ibnul Humam (wafat pada tahun 861 Hijriyah) dengan menyusun kitab yang diberi nama At Tahrir.
Dalam kaitan dengan pembahasan Ilmu Ushul Fiqh ini, perlu dikemukakan bahwa Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy Syatibiy (wafat pada tahun 760 Hijriyah) telah menyusun sebuah kitab Ilmu Ushul Fiqh, yang diberi nama Al Muwafaqat. Dalam kitab tersebut selain dibahas kaidah-kaidah juga dibahas tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Kemudian perlu pula diketahui kitab-kitab Ilmu Ushul Fiqh yang disusun oleh para ulama pada masa belakangan ini, antara lain: kitab Irsyadul Fuhul i/a Tahqiqi/ Haq min 'I/mil Ushu/ oleh Imam Muhammad bin' Aliy Asy Syaukaniy (wafat pada tahun 1255 Hijriyah), kitab Tashilu/ Wushu/ i/a 'Ilmi/ Ushu/ oleh Syaikh Muhammad 'Abdur Rahman Al Mihlawiy (wafat pada tahun 1920 Hijriyah); kitab Ushu/u/ Fiqh oleh Syaikh Muhammad Al Khudlariy Bak (wafat pada tahun 1345 Hijriyah/ 1927 Masehi) dan kitab-kitab Ilmu Ushul Fiqh yang lain.
BAB-VII
KETERKAITAN AQIDAH DAN SYARIAH
Antara aqidah dan syariah jelas terkait dengan ikatan yang sangat kuat. Boleh dibilang tidak ada aqidah tanpa syariah, dan tidak ada syariah tanpa aqidah. Keduanya ibarat dua sisi mata koin yang tidak terpisahkan. Sayangnya, dalam implementasinya, seringkali antara keduanya menjadi terpisah. Syariah adalah Penjelasan Aqidah Contoh yang sederhana ketika membahas masalah hal-hal yang membatalkan iman. Disebutkan bahwa di antara yang membatalkan syahadat dan iman seseorang adalah bila seseorang melakukan kemusyrikan. Secara ilmu aqidah, pernyataan ini benar. Namun bisa menjadi masalah besar dalam implementasinya bila tidak diiringi dengan pemahaman syariah yang benar.
Orang yang menyembah kuburan, menggunanakan jin, jimat, mantera, sihir memang termasuk dikategorikan orang yang melakukan perbuatan syirik. Dan oleh karena itu, secara ilmu aqidah, perbuatan itu dikatakan membatalkan iman dan syahadat. Namun yang menjadi pertanyaan adalah: bila ada orang datang ziarah kubur lalu di dalam doanya terselip sebuah lafadz yang menyiratkan dia telah meminta kepada kuburan, apakah bisa kita vonis iman telah batal dan dia boleh kita sebut sebagai orang kafir? Apakah semua orang yang berpraktek seperti dukun yang mengobati orang dengan menggunakan jin juga bisa kita tuduh sebagai orang kafir? Apakah seorang yang mengagumi bintang film, artis dan tokoh favoritnya bisa kita jebloskan begitu saja sebagai orang non muslim, lantaran lebih cinta kepada selain Allah dan Rasulnya? Apakah rakyat Indonesia yang negaranya tidak menjalakan hukum Islam boleh juga dikatakan sebagai orang kafir? Dan apakah orang yang tidak ikut bai’at kepada suatu kelompok tertentu, juga bisa dikatakan sebagai orang kafir?
Ketika kita membahas masalah syirik dalam kajian aqidah, jelas bahwa syirik itu membatalkan iman dan syahadat. Namun apakah seorang muslim yang kedapatan masih melakukan semua tindakan bernilai syirik, bisa begitu saja dimasukkan sebagai orang yang batal imannya dan menjadi orang kafir? Tentu tidak demikian. Nanti di dalam ilmu syariah kita akan masuk kepada pembahasan bahwa untuk menjatuhkan vonis kafir tidak bisa begitu saja dilakukan. Harus ada sebuah sistem dan tata aturan yang baku dan dijalankan sesuai dengan prosedurnya. Harus ada pengadilan (mahkamah) syariah, bukti, saksi ahli, tuduhan, hak jawab, dan seterusnya.
Apa yang dibahas dalam kajian aqidah boleh dibilang baru mencakup prinsip dasarnya saja. Sedangkan implementasi teknisnya harus dibahas secara rinci dan detail. Dan itu adalah tugas ilmu syariah. Jadi doktrin aqidah tidak bisa berjalan dengan benar tanpa petunjuk teknis, dan itu adalah syariah. Peristiwa pengeboman di negara kita yang dituduhkan kepada sebagian orang yang mengaku beragama Islam, adalah salah satu bentuk ketidak-singkronan antara doktrin aqidah dan dalam syariah. Di dalam syariah dikenal adanya kafir harbi dan kafir zimmi. Kafir harbi harus dibunuh karena bila tidak dibunuh, maka dia akan membunuh kita lebih dahulu. Namun membunuh kafir harbi hanya dibenarkan syariah ketika dilakukan di medan pertempuran yang sesungguhnya, bukan di wilayah yang damai.
Membunuh kafir harbi di dalam wilayah damai di luar wilayah pertempuran adalah sebuah pelanggaran syariah. Demikian juga dengan kafir zimmi, dalam ilmu syariah diharamkan untuk dibunuh, sebagaimana haramnya membunuh sesama muslim. Membunuh kafir zimmi adalah sebuah pelanggaran syariah. Meski doktrin dasar dalam aqidah mengatakan bahwa kita wajib memengangi orang kafir. Pendeknya, apa yang didoktrinkan di dalam kajian aqidah, harus dijabarkan terlebih dahulu secara rinci dan detail. Dan penjabaran serta perincian itu dilakukan dalam kajian syariah. Itulah pentingnya syariah dalam kajian aqidah. Tema Aqidah dan Syariah Ilmu aqidah berbicara tentang tema-tema besar, misalnya tentang tauhid atau memurnikan iman dari segala bentuk syirik (mempersekutukan Allah).
Adapun ilmu syariah umumnya berbicara tentang teknis yang lebih detail dari bentuk iman. Ilmu aqidah berbicara tentang siapa Allah, lengkap dengan segala sifat-sifat dan nama-namaNya. Sedangkan ilmu syariah berbicara tentang apa maunya Allah, yang terperinci dalam perintah-perintah secara teknis. Ilmu aqidah banyak berbicara tentang hal-hal yang ghaib dan harus diimani sebagai bentuk keimanan kita kepada kitabullah dan sunnah rasulullah SAW, sedangkan ilmu syariah lebih banyak bicara pada tataran yang nyata, terlihat, terukur, bisa disentuh, ditangkap oleh paca indera. Misalnya, ilmu aqidah memperkenalkan kita kepada adanya jenis makhluk Allah yang ghaib dan wajib kita imani. Baik yang ada di sekitar kita saat ini seperti adanya jin, malaikat, qarin, ruh, ataupun yang akan nanti kita alami setelah kematian, seperti alam kubur, alam barzakh, padang mahsyar, jembatan shirathal mustaqim, hisab, timbangan, haudh (mata air), surga, neraka. Sedangkan ilmu syariah bicara tentang berapa nisab zakat emas dan hasil pertanian, tentang membedakan darah haidh dan darah istihadhah, tentang jumlah putaran tawaf di sekeliling ka’bah, jumlah batu kerikil yang harus dilontarkan, terbit dan tenggelamnya matahari yang menandakan masuk dan keluarnya waktu shalat.
Ilmu aqidah berbicara tentang posisi seseorang terhadap Allah SWT, Rasululah SAW, dan kitabullah. Hasilnya, seseorang dikatakan beriman tergantung apakah dia menerima Allah sebagai tuhannnya atau tidak. Demikian juga dengan posisi seseorang kepada nabi Muhammad, apakah Muhammad SAW diposisikan sebagai utusan resmi tuhan sehingga dipatuhi dan ditaati serta dijadikan sumber rujukan hidup, ataukah diposisikan sekedar sebagai tokoh yang dikagumi tanpa mengakui kalau posisinya sebagai utusan resmi tuhan dari langit? Ilmu aqidah berbicara tentang Al-Quran, apakah sekedar sebagai bacaan mulia yang diperlombakan dan selesai begitu saja, ataukah sebagai sumber dari segala sumber hukum dan dan pedoman hidup yang mengatur semua sisi kehidupan. Keimanan seseorang akan ditetapkan berdasarkan bagaimana dia memposisikan diri terhadap ketiganya, yaitu Allah, Rasulullah dan kitabullah.
BAB-VIII
SYARIAT DAN FIQH
Syari'at dan Fiqh memiliki ikatan yang kuat dan sulit untuk dipisahkan, namun diantara keduanya terdapat perbedaan yang mendasar. Meskipun syariat dan fiqh memiliki ikatan yang kuat dan sulit dipisahkan, namun diantara keduanya terdapat perbedaan mendasar. Kata syariat (Ar: asy-syari'ah) secara etimologis berarti sumber/aliran air yang digunakan untuk minum. Dalam perkembangannya, kata syariat digunakan orang Arab untuk mengacu kepada jalan (agama) yang lurus (at-tariqah al-mustaqimah), karena kedua makna tersebut mempunyai keterkaitan makna. Sumber/aliran air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk memelihara keselamatan jiwa dan tubuh mereka, sedangkan at-tariqah al-mustaqimah merupakan kebutuhan pokok yang akan menyelamatkan dan membawa kebaikan bagi umat manusia. Dari akar kata ini, syariat diartikan sebagai agama yang lurus yang diturunkan Allah SWT bagi umat manusia.
Secara terminologis, Imam asy-Syatibi menyatakan bahwa syariat sama dengan agama. Sedangkan Manna al-Qattan (ahli fiqh dari Mesir) mendefinisikan syariat sebagai segala ketentuan Allah SWT bagi hamba-Nya yang meliputi masalah akidah, ibadah, akhlak dan tata kehidupan umat manusia untuk mencapai kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Kemudian Fathi ad-Duraini menyatakan bahwa syariat adalah segala yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW berupa wahyu, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi SAW yang diyakini kesahihannya.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa syariat adalah an-nusus al-muqaddasah (teks-teks suci) yang dikandung oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Berdasarkan definisi syariat tersebut, ulama fiqh dan usul fiqh menyatakan bahwa syariat merupakan sumber dari fiqh. Alasannya, fiqh merupakan pemahaman yang mendalam terhadap an-nusus al- muqaddasah dan merupakan upaya mujtahid dalam menangkap makna serta illat yang dikandung oleh an-nusus al-muqaddasah tersebut. Dengan demikian, fiqh merupakan hasil ijtihad ulama terhadap ayat Al-Qur'an atau sunnah Nabi SAW.
Atas dasar perbedaan tersebut, ulama fiqh menyatakan bahwa syariat dan fiqh tidak bisa disamakan. Alasannya, syariat bersumber dari Allah SWT dan Rasul-Nya, sedangkan fiqh merupakan hasil pemikiran mujtahid dalam memahami ayat Al-Qur'an atau hadits Nabi SAW. Menurut Fathi ad-Duraini, sebelum dimasuki oleh pemikiran manusia, syariat selamanya bersifat benar. Sedangkan fiqh, karena sudah merupakan hasil pemikiran manusia, bisa salah dan bisa benar. Namun demikian, menurut Muhammad Yusuf Musa (ahli fiqh dari Mesir) syariat dan fiqh mempunyai keterkaitan yang erat, karenanya fiqh tidak bisa dipisahkan dari syariat.
BAB-IX
TERMINOLOGI ILMU FIQH
TERMINOLOGI ILMU FIQH
(Arab: al-fiqh = paham yang mendalam). Salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun hubungan manusia dengan Penciptanya. Ada beberapa definisi fiqh yang dikemukakan ulama fiqh sesuai dengan perkembangan arti fiqh itu sendiri. Misalnya, Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya. Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan, yaitu aqidah, syariat dan akhlak.
Fiqh di zamannya dan di zaman sebelumnya masih dipahami secara luas, mencakup bidang ibadah, muamalah dan akhlak. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan pembidangan ilmu yang semakin tegas, ulama ushul fiqh mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Definisi tersebut dikemukakan oleh Imam al-Amidi, dan merupakan definisi fiqh yang populer hingga sekarang. Ulama usul fiqh menguraikan kandungan definisi ini sebagai berikut:
Fiqh di zamannya dan di zaman sebelumnya masih dipahami secara luas, mencakup bidang ibadah, muamalah dan akhlak. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan pembidangan ilmu yang semakin tegas, ulama ushul fiqh mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Definisi tersebut dikemukakan oleh Imam al-Amidi, dan merupakan definisi fiqh yang populer hingga sekarang. Ulama usul fiqh menguraikan kandungan definisi ini sebagai berikut:
- Fiqh merupakan suatu ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Karenanya dalam kajian fiqh para fuqaha menggunakan metode-metode tertentu, seperti qiyas, istihsan, istishab, istislah, dan sadd az-Zari'ah (az-Zari'ah);
- Fiqh adalah ilmu tentang hukum syar'iyyah, yaitu Kalamullah/Kitabullah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah untuk berbuat, larangan, pilihan, maupun yang lainnya. Karenanya, fiqh diambil dari sumber-sumber syariat, bukan dari akal atau perasaan;
- Fiqh adalah ilmu tentang hukum syar'iyyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah. Atas dasar itu, hukum aqidah dan akhlak tidak termasuk fiqh, karena fiqh adalah hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari proses istidlal atau istinbath (penyimpulan) dari sumber-sumber hukum yang benar;
- Fiqh diperoleh melalui dalil yang tafsili (terperinci), yaitu dari Al-Qur'an, sunnah Nabi SAW, qiyas, dan ijma' melalui proses istidlal, istinbath, atau nahr (analisis). Yang dimaksudkan dengan dalil tafsili adalah dalil yang menunjukkan suatu hukum tertentu. Misalnya, firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 43: "..... dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat....." Ayat ini disebut tafsili karena hanya menunjukkan hukum tertentu dari perbuatan tertentu pula, yaitu shalat dan zakat adalah wajib hukumnya.
Dengan demikian menurut para ahli usul fiqh, hukum fiqh tersebut tidak terlepas dari an-Nusus al-Muqaddasah (teks-teks suci). Karenanya, suatu hukum tidak dinamakan fiqh apabila analisis untuk memperoleh hukum itu bukan melalui istidlal atau istinbath kepada salah satu sumber syariat. Berdasarkan hal tersebut, menurut Fathi ad-Duraini (ahli fiqh dan usul fiqh dari Universitas Damascus), fiqh merupakan suatu upaya memperoleh hukum syara' melalui kaidah dan metode usul fiqh. Sedangkan istilah fiqh di kalangan fuqaha mengandung dua pengertian, yaitu: 1. Memelihara hukum furu' (hukum keagamaan yang tidak pokok) secara mutlak (seluruhnya) atau sebagiannya; dan 2. Materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat qath'i (pasti) maupun yang bersifat dzanni (relatif) (Qath'i dan Zanni). Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa (ahli fiqh dari Yordania), fiqh meliputi: 1. Ilmu tentang hukum, termasuk usul fiqh; dan 2. Kumpulan hukum furu'.
BAB-X
FIQIH MUAMALAH DAN FIQIH SIYASAH
FIQIH MUAMALAH DAN FIQIH SIYASAH
Kata muamalah berasal dari bahasa Arab: ‘amala – yu’amilu – mu’amalatan (al-mu’amalah), yang berarti menyikapi, memperlakukan, bergaul, berinteraksi, dan semacamnya. Bidang muamalah dalam fiqih Islam secara umum mencakup bidang pergaulan dan interaksi sesama manusia di dalam aspek-aspek kehidupan umum, seperti aspek adat istiadat dan kebiasaan, sosial dan kemasyarakatan, budaya, kesenian dan hiburan, ekonomi dan perdagangan, pendidikan dan pengajaran, politik dan pengelolaan pemerintahan, dan lain-lain.
Meskipun dalam sebagian kitab ulama, istilah muamalah lebih dibatasi maknanya pada bab aktvitas-aktivitas perekonomian dan perdagangan seperti jual beli dan transaksi-transaksi bisnis lainnya, namun kami menggunakannya disini dengan mafhum dan pengertian umum seperti yang telah kami jelaskan diatas. Dimana bidang muamalah dalam fiqih Islam biasanya dipahami sebagai “lawan” dari bidang ibadah atau ubudiyah (aktivitas ritual). Sehingga kaidah fiqih yang diterapkan untuk bidang muamalah secara umum juga merupakan kebalikan dari kaidah yang digunakan untuk bidang ibadah.
Jika kaidah fiqih yang dikenal dalam bidang ibadah berbunyi: Al-ashlu fil-‘ibadat al-man’u awil-hadzru, illa ma dallad-dalilu ‘ala masyru’iyyatih: Hukum asal atau dasar dalam hal ibadah adalah larangan (yakni setiap aktivitas ibadah ritual di dalam Islam adalah terlarang) kecuali yang memang disyariatkan berdasarkan dalil (Al-Qur’an dan As-Sunnah). Maka kaidah yang berlaku di bidang muamalah (baca: selain ibadah ritual) adalah berbunyi: Al-ashlu fil-mu’amalati al-ibahatu illa ma dallad-dalilu ‘ala ma’ihi au tahrimih: Hukum asal atau dasar di bidang muamalah adalah hukum boleh kecuali jika ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Jadi yang kami maksudkan dengan istilah fiqih muamalah adalah: setiap pembahasan dan kajian fiqih dan hukum Islam dalam bidang-bidang kehidupan umum tersebut diatas. Adapun kata siyasah juga berasal dari bahasa Arab: sasa – yasusu – siyasatan (as-siyasah), yang berarti: mengatur, memimpin, dan semacamnya.
Namun dalam pemakaian, istilah as-siyasah kemudian lebih dikenal dengan mafhum dan pengertian khusus, yakni kepemimpinan negara dan pengaturan pemerintahan, atau yang lebih dikenal dengan istilah politik. Maka yang kami maksud dengan istilah fiqih siyasah adalah: pembahasan dan kajian fiqih atau hukum Islam dalam bidang-bidang yang terkait dengan dunia politik, kepemimpinan negara dan pengaturan pemerintahan. Meskipun sebenarnya bidang siyasah sudah masuk dalam mafhum dan pengertian umum bidang muamalah yang kami jelaskan diatas. Namun kemudian dipisahkan menjadi bidang tersendiri, karena bidang politik, kenegaraan dan pemerintahan memiliki urgensi khusus dan titik tekan istimewa di dalam ajaran Islam jika dibandingkan dengan bidang-bidang muamalah yang lainnya. Ditambah lagi, dalam kajian fiqih Islam, bidang urusan politik, kenegaraan dan pemerintahan telah menjadi bidang spesialisasi ilmu tersendiri, yang terkenal dengan istilah fiqih siyasah syar’iyah (fiqih tentang sistem politik Islam).
Oleh karena itu banyak ulama Islam yang menulis kitab-kitab khusus di bidang fiqih siyasah syar’iyah ini. Sebut saja misalnya: Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah dan Al-Imam Abu Ya’la Al-Farra’ rahimahullah dalam kitab masing-masing dengan judul yang sama: Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Syaikhul Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam: As-Siyasah Asy-Syar’iyyah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Ath-Thuruq Al-Hukmiyyah, dan lain-lain. Demikianlah jawaban singkat yang bisa kami berikan, semoga terpahami dan bermanfaat. Sekaligus kami mohon maaf atas keterlambatan jawaban ini. Wallahu a’lam, wa Huwal-Muwaffiq ilaa aqwamith-thariiq, wal-Haadii ilaa sawaa-issabiil.
BAB-XI
SIYASAH DALAM PANDANGAN ISLAM
SIYASAH DALAM PANDANGAN ISLAM
Pengertian Siyasah Jika yang dimaksud dengan siyasah ialah mengatur segenap urusan ummat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Bahkan, Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan ummat. Akan tetapi jika siyasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tetapi, Islam juga tidak pernah melepaskan diri dari masalah kekuasaan.
Islam dan Kekuasaan Orientasi utama kita terkait dengan masalah kekuasaan ialah menegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ialah kekuasaan Allah. Sementara, manusia pada dasarnya sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Bahkan Islam menentang adanya penguasaan mutlak seorang manusia atas manusia yang lain, karena yang demikian ini bertentangan dengan doktrin Laa ilaha illallah yang telah membebaskan manusia dari segenap thaghut (tiran). Sehingga, kekuasaan manusia yang menentang hukum-hukum Allah adalah tidak sah. Tujuan Siyasah dalam Islam Islam memandang kehidupan dunia sebagai ladang bagikehidupan akhirat. Kehidupan dunia harus diatur seapik mungkin sehingga manusia bisa mengabdi kepada Allah secara lebih sempurna. Tata kehidupan di dunia tersebut harus senantiasa tegak diatas aturan-aturan din. Konsep ini sering dianggap mewakili tujuan siyasah dalam Islam: iqamatud din (hirasatud din) wa siyasatud dunya (menegakkan din dan mengatur urusan dunia).
Hubungan antara Islam dan Politik Islam merupakan agama yang mencakup keseluruhan sendi kehidupan manusia (syamil). Islam bukanlah sekedar agama kerahiban yang hanya memiliki prosesi-prosesi ritual dan ajaran kasih-sayang . Islam bukan pula agama yang hanya mementingkan aspek legal formal tanpa menghiraukan aspek-aspek moral. Politik, sebagai salah satu sendi kehidupan, dengan demikian juga diatur oleh Islam. Akan tetapi, Islam tidak hanya terbatas pada urusan politik. Islam Politik atau Politik Islam? Ketika seseorang mendengar istilah Islam Politik, tentu ia akan segera memahaminya sebagai Islam yang bersifat atau bercorak politik. Dalam hal ini, Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi, politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tanpa ada corak lainnya yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian ialah Islam yang parsial. Munculnya varian-varian Islam dengan corak politik yang amat kuat pada dasarnya didorong oleh kelemahan atau bahkan keterpurukan politik umat Islam saat ini. Karena kondisi sedemikian ini, politik kemudian menjadi salah satu PR penting umat Islam saat ini, untuk bisa bangkit dari kemundurannya.
Adapun istilah Politik Islam tentu akan segera dipahami sebagai politik ala Islam atau konsep politik menurut Islam. Istilah ini wajar ada karena memang dalam kenyataannya terdapat banyak konsep politik yang kurang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pertanyaan yang selanjutnya muncul ialah apakah Politik Islam itu ada? Apakah Islam mempunyai konsep khusus tentang politik, berbeda dengan konsep-konsep politik pada umumnya? Yang jelas, sampai batasan tertentu, Islam memang memiliki konsep yang khas tentang politik. Akan tetapi, tentu saja Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang senantiasa muncul untuk kemudian bisa melengkapi konsep yang sudah dimiliki, sepanjang tidak bertentangan dengan konsep baku yang sudah ada. Sifat terbuka Islam dalam masalah politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah menetapkan konsep politiknya secara amat rinci dalam segenap masalahnya. Ketidakrincian itu sendiri merupakan bagian dari kebijaksanaan Allah agar Islam bisa mengembangkan konsep politiknya dari waktu ke waktu tanpa harus terkungkung oleh rincian-rincian yang sangat mengikat, sementara kondisi zaman senantiasa berubah dan berkembang. Akan tetapi, tidak pula berarti bahwa Islam sama sekali tidak memiliki rincian dalam masalah-masalah politik. Ada masalah-masalah tertentu yang telah ditetapkan secara rinci dan tidak boleh berubah kapanpun juga, meskipun zamannya berubah. Dalam hal ini, tidaklah benar pandangan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa dalam masalah politik, Islam hanya memiliki nilai-nilai normatif saja, yang bisa diturunkan seluas-luasnya tanpa batasan-batasan yang berarti.
Islam Tidak Bisa Dibangun Secara Sempurna Tanpa Politik Tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi merupakan amanah yang harus diwujudkan. Hukum-hukum tersebut tidak akan mungkin bisa tegak tanpa politik pada umumnya dan kekuasaan pada khususnya. Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa Islam harus ditegakkan dengan dua hal : Al-Qur’an dan pedang. Al-Qur’an merupakan sumber hukum-hukum Allah sedangkan pedang melambangkan kekuatan politik atau kekuasaan yang menjamin tegaknya isi Al-Qur’an.
Hubungan antara Islam dan Politik Islam merupakan agama yang mencakup keseluruhan sendi kehidupan manusia (syamil). Islam bukanlah sekedar agama kerahiban yang hanya memiliki prosesi-prosesi ritual dan ajaran kasih-sayang . Islam bukan pula agama yang hanya mementingkan aspek legal formal tanpa menghiraukan aspek-aspek moral. Politik, sebagai salah satu sendi kehidupan, dengan demikian juga diatur oleh Islam. Akan tetapi, Islam tidak hanya terbatas pada urusan politik. Islam Politik atau Politik Islam? Ketika seseorang mendengar istilah Islam Politik, tentu ia akan segera memahaminya sebagai Islam yang bersifat atau bercorak politik. Dalam hal ini, Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi, politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tanpa ada corak lainnya yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian ialah Islam yang parsial. Munculnya varian-varian Islam dengan corak politik yang amat kuat pada dasarnya didorong oleh kelemahan atau bahkan keterpurukan politik umat Islam saat ini. Karena kondisi sedemikian ini, politik kemudian menjadi salah satu PR penting umat Islam saat ini, untuk bisa bangkit dari kemundurannya.
Adapun istilah Politik Islam tentu akan segera dipahami sebagai politik ala Islam atau konsep politik menurut Islam. Istilah ini wajar ada karena memang dalam kenyataannya terdapat banyak konsep politik yang kurang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pertanyaan yang selanjutnya muncul ialah apakah Politik Islam itu ada? Apakah Islam mempunyai konsep khusus tentang politik, berbeda dengan konsep-konsep politik pada umumnya? Yang jelas, sampai batasan tertentu, Islam memang memiliki konsep yang khas tentang politik. Akan tetapi, tentu saja Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang senantiasa muncul untuk kemudian bisa melengkapi konsep yang sudah dimiliki, sepanjang tidak bertentangan dengan konsep baku yang sudah ada. Sifat terbuka Islam dalam masalah politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah menetapkan konsep politiknya secara amat rinci dalam segenap masalahnya. Ketidakrincian itu sendiri merupakan bagian dari kebijaksanaan Allah agar Islam bisa mengembangkan konsep politiknya dari waktu ke waktu tanpa harus terkungkung oleh rincian-rincian yang sangat mengikat, sementara kondisi zaman senantiasa berubah dan berkembang. Akan tetapi, tidak pula berarti bahwa Islam sama sekali tidak memiliki rincian dalam masalah-masalah politik. Ada masalah-masalah tertentu yang telah ditetapkan secara rinci dan tidak boleh berubah kapanpun juga, meskipun zamannya berubah. Dalam hal ini, tidaklah benar pandangan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa dalam masalah politik, Islam hanya memiliki nilai-nilai normatif saja, yang bisa diturunkan seluas-luasnya tanpa batasan-batasan yang berarti.
Islam Tidak Bisa Dibangun Secara Sempurna Tanpa Politik Tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi merupakan amanah yang harus diwujudkan. Hukum-hukum tersebut tidak akan mungkin bisa tegak tanpa politik pada umumnya dan kekuasaan pada khususnya. Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa Islam harus ditegakkan dengan dua hal : Al-Qur’an dan pedang. Al-Qur’an merupakan sumber hukum-hukum Allah sedangkan pedang melambangkan kekuatan politik atau kekuasaan yang menjamin tegaknya isi Al-Qur’an.
BAB-XII
ADAT DALAM ISLAM
ADAT DALAM ISLAM
Dalam ushul fiqih terdapat sebuah kaidah asasi al-‘adat muhakkamat (=adat dapat dihukumkan) atau al-‘adat syari’at muhakkamat (=adat merupakan syariat yang dihukumkan). Kaidah tersebut kurang lebih bermakana bahwa adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum (hukum Islam). Adat bisa mempengaruhi materi hukum, secara proporsional. Hukum Islam tidak memposisikan adat sebagai faktor eksternal non-implikatif, namun sebaliknya, memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan sedemikian inilah antara lain yang menyebabkan hukum Islam bersifat fleksibel. Dalam bahasa Arab, al-‘adat sering pula dipadankan dengan al-‘urf. Dari kata terakhir itulah, kata al-ma’ruf – yang sering disebut dalam Al-Qur’an – diderivasikan.
Oleh karena itu, makna asli al-ma’ruf ialah segala sesuatu yang sesuai dengan adat (kepantasan). Kepantasan ini merupakan hasil penilaian hati nurani. Mengenai hati nurani, Rasulullah pernah memberikan tuntunan agar manusia bertanya kepada hati nuraninya ketika dihadapkan pada suatu persoalan (mengenai baik dan tidak baik). Beliau juga pernah menyatakan bahwa keburukan atau dosa ialah sesuatu yang membuat hati nurani menjadi gundah (tidak sreg). Dalam perkembangannya, al-‘urf kemudian secara general digunakan dengan makna tradisi, yang tentu saja meliputi tradisi baik (al-urf al-shahih) dan tradisi buruk (al-‘urf al-fasid). Dalam konteks ini, tentu saja al-ma’ruf bermakna segala sesuatu yang sesuai dengan tradisi yang baik. Arti “baik” disini adalah sesuai dengan tuntunan wahyu. Amr bi al-ma’ruf berarti memerintahkan sesama manusia untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai wahyu. Nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat merupakan manifestasi hati-hati nurani masyarakat tersebut dalam konteks kondisi lingkungan yang melingkupi masyarakat tersebut. Kondisi lingkungan yang berbeda pada masyarakat yang berbeda akan menyebabkan variasi pada nilai-nilai kepantasan yang dianut.
Karena itu, tradisi pada suatu masyarakat bisa berbeda dengan tradisi pada masyarakat yang lain. Sebagai sebuah contoh, apabila Al-Qur’an menyatakan “wa ‘asyiru hunna bi al-ma’ruf (=Dan pergaulilah isteri-isteri kalian secara ma’ruf)” maka yang dimaksud adalah tuntutan kepada para suami untuk memperlakukan isteri-isteri mereka sesuai dengan nilai-nilai kepantasan yang berlaku dalam masyarakat, yang mana nilai-nilai itu bisa jadi berbeda dengan yang ada pada masyarakat lainnya. Namun perlu diingat bahwa nilai-nilai kepantasan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai wahyu (Al-Qur’an dan Sunnah Nabi). Karakter hukum Islam yang akomodatif terhadap adat (tradisi) amat bersesuaian dengan fungsi Islam sebagai agama universal (untuk seluruh dunia). “Wajah” Islam pada berbagai masyarakat dunia tidaklah harus sama (monolitik). Namun, keberagaman tersebut tetaplah dilingkupi oleh wihdat al-manhaj (kesatuan manhaj) yaitu al-manhaj al-Nabawiy al-Muhammadiy.
Berangkat dari kesadaran “Bhinneka Tunggal Ika” inilah, Islam tidaklah harus disamakan dengan Arab. Islam merupakan sebuah manhaj yang bersifat universal, yang tidak bisa dibatasi oleh ke-Arab-an semata (Namun perlu diingat bahwa Arab [terutama bahasa Arab] dalam beberapa hal memang mempunyai posisi strategis dalam Islam). Namun, harus disadari pula bahwa Islam diturunkan kepada Muhammad saw, seorang Arab, ditengah-tengah bangsa Arab. Implikasinya, Nabi tidak akan bisa lepas dari konteks/lingkungan Arab. Hal ini nantinya juga akan berpengaruh pada pewahyuan, baik Al-Qur’an maupun Al-Sunnah (sebagaimana dikatakan oleh para ushuliyyun dan mutakallimun bahwa perkataan [yang bukan Al-Qur’an] dan perbuatan Nabi merupakan “wahyu” karena Nabi senantiasa mendapat penjagaan dan ilham dari Allah).
Berangkat dari kesadaran “Bhinneka Tunggal Ika” inilah, Islam tidaklah harus disamakan dengan Arab. Islam merupakan sebuah manhaj yang bersifat universal, yang tidak bisa dibatasi oleh ke-Arab-an semata (Namun perlu diingat bahwa Arab [terutama bahasa Arab] dalam beberapa hal memang mempunyai posisi strategis dalam Islam). Namun, harus disadari pula bahwa Islam diturunkan kepada Muhammad saw, seorang Arab, ditengah-tengah bangsa Arab. Implikasinya, Nabi tidak akan bisa lepas dari konteks/lingkungan Arab. Hal ini nantinya juga akan berpengaruh pada pewahyuan, baik Al-Qur’an maupun Al-Sunnah (sebagaimana dikatakan oleh para ushuliyyun dan mutakallimun bahwa perkataan [yang bukan Al-Qur’an] dan perbuatan Nabi merupakan “wahyu” karena Nabi senantiasa mendapat penjagaan dan ilham dari Allah).
Sebagai contoh, Al-Qur’an mau tidak mau mesti diturunkan dalam bahasa Arab agar bisa dipahami oleh komunitas dimana Al-Qur’an diturunkan. Demikian juga perkataan Nabi, mesti dinyatakan dalam bahasa Arab. Demikian pula penyebutan nama-nama benda dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits, tidaklah akan keluar dari perbendaharaan yang bisa dipahami oleh masyarakat Arab saat itu. Kalaupun ada istilah yang tidak dimengerti, maka para sahabat mesti langsung menanyakannya kepada Nabi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap bentuk-bentuk tasyri’ yang melibatkan nama-nama benda, haruslah dilakukan secara esensial, lepas dari kungkungan bahasa, tempat, dan zaman.
Sebuah contoh, tatkala Nabi memberitakan bahwa habbat al-sauda’ (jintan hitam) merupakan suatu obat yang mujarab bagi penyakit tertentu, maka itu tidak berarti bahwa tidak ada obat lain yang juga bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Adalah sangat mungkin akan ada berpuluh-puluh obat yang bisa berfungsi seperti habbat al-sauda’. Esensi dari berita Nabi tentang habbat al-sauda’ adalah zat yang dikandung oleh habbat al-sauda’, yang bisa menyembuhkan penyakit tertentu, dan zat tersebut bisa juga terdapat pada benda lain. Atau barangkali esensinya lebih luas dari itu, yakni perintah Nabi agar umatnya giat melakukan riset di bidang farmasi untuk menemukan berbagai benda di alam ini, yang berkhasiat untuk mengobati penyakit.
Sebuah contoh, tatkala Nabi memberitakan bahwa habbat al-sauda’ (jintan hitam) merupakan suatu obat yang mujarab bagi penyakit tertentu, maka itu tidak berarti bahwa tidak ada obat lain yang juga bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Adalah sangat mungkin akan ada berpuluh-puluh obat yang bisa berfungsi seperti habbat al-sauda’. Esensi dari berita Nabi tentang habbat al-sauda’ adalah zat yang dikandung oleh habbat al-sauda’, yang bisa menyembuhkan penyakit tertentu, dan zat tersebut bisa juga terdapat pada benda lain. Atau barangkali esensinya lebih luas dari itu, yakni perintah Nabi agar umatnya giat melakukan riset di bidang farmasi untuk menemukan berbagai benda di alam ini, yang berkhasiat untuk mengobati penyakit.
Namun pola pemahaman esensial ini tidak boleh sampai kepada interpretasi bahwa, misalnya, habbat al-sauda’ tidak lagi efektif untuk obat, karena Nabi sudah jelas-jelas mengatakan efektivitasnya. Jadi, interpretasi boleh meluas (berangkat dari teks) namun tidak boleh membatalkan teks itu sendiri (karena justeru teks itulah titik tolak interpretasi). Demikian pula tradisi (sunnah) Nabi secara umum, haruslah dipahami secara esensial. Hal ini tidak lain karena Islam merupakan agama universal dan berlaku selamanya. Dengan pemahaman esensial, syariat akan dapat diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, sampai ke relung-relungnya yang terkecil sekalipun.
Pemahaman esensial juga akan menjadi “mimpi buruk (nightmare)” bagi orang-orang yang hendak melakukan hilat (intrik, manipulasi) terhadap syariat, dengan bertameng pada teks. Adaptasi syariat terhadap adat juga bisa diamati pada materi wahyu. Imam Al-Syathibi dalam Al-Muwafaqat menerangkan bahwa akibat ke-ummi-an bangsa Arab maka wahyu (yang berarti juga syariat) pun bersifat ummi. Maksudnya, wahyu turun dengan tingkat kompleksitas yang sesuai dengan tingkat berpikir bangsa Arab saat itu. Wahyu tidak dituntut untuk dipahami secara njelimet melebihi kemampuan berpikir bangsa Arab saat itu. Meskipun begitu, justeru generasi saat itulah yang merupakan generasi terbaik dalam pemahamannya terhadap wahyu.
Bagaimana Islam Menyikapi Adat? Sebuah diktum yang amat terkenal menerangkan tentang salah satu prinsip Islam: Muhafazhat ‘ala al-qadim al-shalih wa akhdz ‘ala al-jadid al-ashlah (=Memelihara hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik). Artinya, kedatangan Islam tidaklah untuk memberangus adat yang baik yang berlaku pada suatu masyarakat. Islam memandang adat yang baik sebagai suatu bentuk kreasi manusia dalam konteks lingkungannya (fisik dan nonfisik). Karena itu, Islam bersifat acceptable pada berbagai bentuk masyarakat yang ada di dunia ini kapanpun juga. Atas dasar ini, Islam memang pantas menjadi agama universal dan berlaku selamanya. Dalam perkembangan adat (akibat interaksi antar adat yang berbeda), Islam mengajarkan untuk menjaga adat lama yang baik, sebagai suatu orisinalitas yang akan mewarnai kehidupan. Apabila terdapat suatu adat baru (yang baik) maka hendaknya sebisa mungkin diterima untuk didampingkan dengan adat yang lama (yang juga baik), sehingga akan memperkaya khazanah budaya masyarakat tersebut. Namun apabila adat baru (yang baik) itu mesti menggantikan sesuatu yang lama, maka yang baru tersebut baru boleh diterima apabila telah diyakini lebih baik daripada yang lama. Dengan sikap sedemikian, manusia akan selalu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.
BAB-XIII
PERILAKU AKHLAQI PADA DIRI SEORANG MUJTAHID
PERILAKU AKHLAQI PADA DIRI SEORANG MUJTAHID
Para ulama menegaskan bahwa seorang mufti dilarang berfatwa apabila sedang dalam keadaan marah, gelisah yang amat dalam, lapar yang sangat, dan yang semacamnya. Sebaliknya, seseorang dianjurkan untuk tidak meminta fatwa kepada orang yang suka bergurau, karena dikhawatirkan gurauannya akan mempengaruhi fatwanya. Pernyataan diatas secara esensial berarti bahwa seorang mufti haruslah berada dalam kondisi mental emosional yang “prima” pada saat mengeluarkan fatwanya. Kesempurnaan mental emosional bagi seorang mufti merupakan prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kondisi mental emosional yang buruk pada diri seorang mufti nantinya akan turut mempengaruhi fatwanya. Kondisi mental emosional yang baik merupakan iklim yang kondusif sekaligus mitra yang baik bagi rasionalitas hukum (legal rationality) yang dimiliki oleh seorang mufti.
Sebaliknya, kondisi mental emosional yang buruk akan menjadi perusak bagi rasionalitas hukum seorang mufti. Salah satu sifat mental positif yang wajib dimiliki oleh seorang mufti adalah sifat cinta (hubb, rahmah) kepada sesama manusia dan makhluk Allah. Minimal, cintanya itu harus sama dengan cintanya kepada dirinya sendiri. Akan lebih baik lagi, kalau dia bisa bersikap itsar (melebihi dari rasa cinta kepada dirinya sendiri). Seorang mujtahid harus selalu memandang sesama manusia dan alam dengan penuh kasih sayang dan rasa-rasa positif-optimis. Sifat mental yang demikian ini akan menjadi iklim yang bagus bagi obyektivitas rasionalitas hukum seorang mujtahid. Agaknya, Rasulullah benar-benar merupakan teladan yang sangat baik dalam masalah ini. Beliau senantiasa merasa berat untuk memikulkan beban yang berat dipundak umatnya. Beliau merupakan pribadi yang sangat empatik terhadap umatnya. Beliau amat bahagia melihat kebahagiaan umatnya, sebaliknya, merasa sedih melihat penderitaan umatnya.
Disebutkan dalam sebuah hadits shahih bahwa dalam mi’raj, Rasulullah telah mengajukan dispensasi frekuensi shalat wajib – yang akhirnya ditetapkan hanya menjadi lima kali sehari semalam . Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah tidak senang melihat tiga orang sahabatnya yang berniat untuk berlebihan dalam beragama, sebaliknya, dengan penuh kasih-sayang menganjurkan kepada ketiganya untuk bersikap wajar dalam beragama. Penganiayaan orang-orang Thaif kepada Nabi, bahkan, tidaklah membuat Nabi marah dan mengiyakan adzab Allah kepada mereka. Sebaliknya, Nabi malah mendoakan turunnya petunjuk dan kebaikan atas mereka karena Nabi sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang belum mengerti. Kejadian yang serupa dengan ini adalah tindakan Nabi atas seorang Badui yang buang air kecil di masjid Nabi. Beberapa contoh tindakan Nabi diatas – dari banyak tindakan serupa yang tak terhitung jumlahnya – menunjukkan betapa besarnya kasih sayang dan empati beliau terhadap umatnya. Kendatipun begitu lapangnya sikap Nabi terhadap para sahabatnya – dan umatnya secara umum – namun Nabi dari sisi pribadi merupakan seorang yang amat zuhud. Hal ini antara lain tergambar dalam sebuah hadits dimana Aisyah ra merasa heran atas usaha beliau yang tak kenal lelah dalam bertaqarrub kepada Allah.
Ketika Aisyah menanyakan hal itu maka Nabi menjawab,”Tidakkah saya ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur?” Begitulah Rasulullah, secara pribadi beliau adalah manusia yang paling zuhud namun pada saat yang sama merupakan manusia yang paling lapang hatinya dalam berdakwah menyeru manusia ke jalan Allah. Landasan syar’i atas sikap yang demikian itu antara lain:
1. Tuntunan Nabi bahwa orang yang bertindak sebagai imam shalat berjamaah hendaknya mempercepat shalatnya. Akan tetapi dalam shalat sendirian, seseorang diberi kebebasan untuk shalat selama mungkin sesuai kehendaknya. Esensi dari tuntunan ini adalah bersikap lapang terhadap banyak orang dan bersikap ketat - namun tidak boleh berlebihan – dalam urusan pribadi.
2. Allah Ta’ala berfirman: “Maka berkat kasih sayang dari Allah engkau telah bersikap lunak terhadap mereka. Seandainya engkau kasar dan berkeras hati tentulah mereka akan menyingkir menjauhimu. Karena itu maafkanlah mereka, mintakanlah mereka ampunan, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu ... “ (Alu Imran : 159) Berdakwalah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah (kebijaksanaan) dan nasihat yang baik ....” (Al-Nahl : 125) “Dan mereka saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran.” (Al-‘Ashr : 3) “Dan mereka saling menasihati dalam kebenaran dan mereka saling menasihati dalam kasih sayang. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Al-Balad : 17) “Pergilah engkau berdua (Musa dan Harun) kepada Fir’aun karena sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berkatalah kepadanya dengan perkataan yang lembut agar dia menjadi ingat atau takut (kepada Tuhannya).” (Thaha : 43 – 44) “... Dan (Allah) tidaklah menjadikan kesempitan atas kamu dalam agama (Islam)”. (Al-Hajj : 78) “... (Allah) menghendaki kemudahan bagi kalian dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagi kalian”. (Al-Baqarah : 185) “Katakanlah (wahai Muhammad) : Siapakah gerangan yang telah mengharamkan perhiasan Allah dan rizki yang baik-baik yang telah Dia anugerahkan untuk hamba-hamba-Nya ? Katakanlah : Semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan secara khusus pada hari kiamat. Demikianlah Aku menjelaskan ayat-ayat(-Ku) kepada kaum yang berilmu. Katakanlah: Rabbku hanyalah mengharamkan segala yang buruk baik yang nampak atau yang tersembunyi, segala dosa, dan perbuatan yang melampaui batas tanpa (alasan) yang benar. Dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang mana Dia tidak menurunkan keterangannya. Dan janganlah mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui.” (Al-A’raf : 32 – 33) “Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah bagimu, demi mendapatkan perkenan isteri-isterimu?” (Al-Tahrim : 1) “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan sesuatu yang baik, yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kalian. Dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Al-Maidah : 87) Nabi saw bersabda: “Bermudah-mudahlah dan jangan mempersulit. Sampaikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang lari (dari Islam)”. “Sesungguhnya aku diutus dengan membawa (din) yang lurus (al-hanifiyyah) dan lapang (al-samhah)”. Di lain sisi, terdapat banyak sekali hadits-hadits Nabi yang mengajarkan untuk bersikap wara’ dan zuhud dalam kehidupan pribadi. Bahkan, Nabi sendiri – secara non eksklusif - telah mencontohkan kehidupan pribadi yang paling wara’ dan zuhud.
Seorang mujtahid harus terbebas dari akhlaq tercela yang berlawanan dengan kasih-sayang. Ia tidak boleh dijangkiti oleh sifat iri-dengki dan dendam terhadap sesama. Sifat-sifat yang demikian ini akan kontraproduktif – destruktif terhadap rasionalitas hukum. Akibatnya, keputusan hukum yang diperoleh akan cacat. Yang patut dicatat dalam masalah kasih-sayang ini adalah ketidakbolehan berlebih-lebihan dalam memanifestasikan kasih-sayang, yang pada dasarnya justru bertentangan dengan hakikat kasih-sayang itu sendiri. Hakikat kasih-sayang disini adalah mewujudkan kebahagiaan hakiki, dunia dan akhirat, bagi sesama. Apabila kasih-sayang itu dimanifestasikan secara berlebih-lebihan sehingga mengancam kebahagiaan hakiki orang lain maka pada dasarnya hal itu adalah destruksi dan bukan kasih-sayang.
Satu tamsil yang sering dipakai untuk menggambarkan hal ini adalah kasih-sayang seorang ibu pada anaknya yang masih kecil. Terkadang si ibu harus mencegah keinginan-keinginan si anak, bahkan sampai anaknya menangis, karena keinginan tersebut bisa membahayakan si anak. Dari sisi pribadi, perilaku wara’ dan zuhud seorang mujtahid menunjukkan ketulusan dan kesungguhannya dalam mengabdi kepada Allah. Dia rela meninggalkan permainan-permainan dunia, yang sebetulnya diperbolehkan, demi melakukan mujahadah menggapai kasih-sayang dan perkenan-Nya. Sebuah ungkapan yang amat terkenal, yang menggambarkan perilaku ini, mengatakan “Seseorang tidak akan mencapai derajat ketaqwaan tertinggi sebelum dia menganggap apa-apa atas sesuatu yang dianggap tidak apa-apa bagi kebanyakan orang”. Namun, perlu dicatat bahwa perilaku ini bukanlah melarang sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Sama sekali tidak.
Satu tamsil yang sering dipakai untuk menggambarkan hal ini adalah kasih-sayang seorang ibu pada anaknya yang masih kecil. Terkadang si ibu harus mencegah keinginan-keinginan si anak, bahkan sampai anaknya menangis, karena keinginan tersebut bisa membahayakan si anak. Dari sisi pribadi, perilaku wara’ dan zuhud seorang mujtahid menunjukkan ketulusan dan kesungguhannya dalam mengabdi kepada Allah. Dia rela meninggalkan permainan-permainan dunia, yang sebetulnya diperbolehkan, demi melakukan mujahadah menggapai kasih-sayang dan perkenan-Nya. Sebuah ungkapan yang amat terkenal, yang menggambarkan perilaku ini, mengatakan “Seseorang tidak akan mencapai derajat ketaqwaan tertinggi sebelum dia menganggap apa-apa atas sesuatu yang dianggap tidak apa-apa bagi kebanyakan orang”. Namun, perlu dicatat bahwa perilaku ini bukanlah melarang sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Sama sekali tidak.
Hal ini dibuktikan oleh bahwasanya dia tidak pernah melarang orang lain dalam melakukan perbuatan tersebut, karena memang diperbolehkan. Dia hanya memilih (ikhtiyar) antara mengerjakan dan meninggalkan, tanpa keyakinan melarangnya sama sekali. Yang terlarang adalah apabila dia meninggalkannya dengan keyakinan atas ketidakbolehannya, padahal diperbolehkan. Perilaku akhlaqi seperti yang dijelaskan diatas merupakan kecenderungan yang terbaik, dibandingkan dengan kecenderungan-kecenderungan lainnya. Sebagian mujtahid ada yang bersikap lapang dalam berfatwa sekaligus bersikap lapang terhadap dirinya sendiri. Sikap yang demikian juga benar, dalam artian dia berusaha memanfaatkan kemurahan Allah berupa nikmat-nikmat dunia bagi dirinya, diiringi rasa syukur yang dalam kepada-Nya, sehingga ketaatannya bisa bertambah.
Hal ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Syathibi dalam buku beliau Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, bab Hukum Mubah. Sebagian mujtahid ada pula yang bersikap ketat dalam berfatwa dan dalam kehidupan pribadinya dia bersikap lebih ketat lagi. Kecenderungan yang demikian juga bisa dimaklumi. Besar kemungkinan dia bersikap ketat dalam berfatwa adalah juga karena kasih-sayangnya yang besar kepada sesama, agar mereka tidak terpedaya oleh kehidupan dunia dan hanya mengabdikan hidup untuk agama, yang ujung-ujungnya adalah kebahagiaan hakiki. Berbagai perbedaan kecenderungan seperti diatas adalah wajar, sesuai dengan sunnatullah dan fitrah manusia itu sendiri. Yang terpenting dari kesemuanya adalah niat yang tulus disertai mujahadah menurut cara-cara yang telah dituntunkan oleh Allah.
Hal ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Syathibi dalam buku beliau Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, bab Hukum Mubah. Sebagian mujtahid ada pula yang bersikap ketat dalam berfatwa dan dalam kehidupan pribadinya dia bersikap lebih ketat lagi. Kecenderungan yang demikian juga bisa dimaklumi. Besar kemungkinan dia bersikap ketat dalam berfatwa adalah juga karena kasih-sayangnya yang besar kepada sesama, agar mereka tidak terpedaya oleh kehidupan dunia dan hanya mengabdikan hidup untuk agama, yang ujung-ujungnya adalah kebahagiaan hakiki. Berbagai perbedaan kecenderungan seperti diatas adalah wajar, sesuai dengan sunnatullah dan fitrah manusia itu sendiri. Yang terpenting dari kesemuanya adalah niat yang tulus disertai mujahadah menurut cara-cara yang telah dituntunkan oleh Allah.
BAB-XIV
MEMBAHAS DALIL-DALIL HUKUM
MEMBAHAS DALIL-DALIL HUKUM
Dalil-dalil hukum (adillat al-ahkam) sering pula disebut dengan sumber-sumber hukum (mashadir al-ahkam). Sepanjang yang dimaksud adalah Al-Qur’an dan Al-Sunnah maka kedua istilah tersebut absah. Namun jika yang dimaksud adalah hal-hal yang kemudian dipahami oleh ushuliyyun sebagai dalil-dalil hukum, yang jenisnya amat banyak, maka istilah adillat al-ahkam merupakan istilah yang lebih tepat.
Alasannya, banyak hal memang bisa berfungsi sebagai dalil (penunjuk) hukum, tidak terbatas pada Al-Qur’an dan Al-Sunnah saja – meskipun asalnya juga dari keduanya. Lain halnya dengan istilah mashadir al-ahkam. Istilah mashadir (sumber) hanya tepat jika dipakai untuk Al-Qur’an dan Al-Sunnah, karena hanya kedua hal itulah yang menjadi sumber dalam syariat. Para ulama ushul berbeda pendapat dalam masalah dalil-dalil hukum. Mereka berselisih tentang apa sajakah yang absah untuk dijadikan sebagai dalil hukum. Kalau diamati dengan teliti, akan tampak bahwa sebagian besar perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan definisi terminologis, dan bukan disebabkan oleh perbedaan esensi. Namun perbedaan definisi terminologis bukanlah satu-satunya penyebab perbedaan pendapat ini, karena ada hal-hal lainnya yang juga turut berperan bagi timbulnya perbedaan pendapat ini. Dalil-dalil hukum yang dimaksud antara lain Al-Qur’an, Al-Sunnah, ijma’, qiyas, madzhab al-shahabiy, istihsan, maslahat al-mursalah, istish-hab, ‘urf, dan syar’u man qablana.
Metode berdalil dengan berbagai dalil hukum selain Al-Qur’an dan Al-Sunnah biasanya disebut sebagai istidlal. Ijtihad, dalam pengertian sebagai usaha optimal untuk memutuskan perkara yang tidak di-nash-kan dalam Al-Qur’an dan Al-Sunnah, tidak lain adalah istidlal itu sendiri. Diantara dalil-dalil hukum diatas, Al-Qur’an dan Al-Sunnah sajalah yang tidak diperselisihkan otoritasnya. Dalil-dalil hukum yang lain tidak ada yang lepas dari perbedaan pendapat para ulama. Keberadaan ijma’(konsensus) diperselisihkan oleh para ulama. Mungkinkah segenap mujtahid pada satu masa bersepakat atas satu hal tanpa ada satupun yang menyalahinya? Mereka yang menjawab “mungkin” kemudian mengemukakan klasifikasi ijma’ atas ijma’ sharih dan ijma’ sukuti. Betapapun serunya perbedaan pendapat dalam masalah ini, paling tidak para ulama bersepakat atas otoritas ijma’ para sahabat Nabi. Permasalahan lain yang juga muncul dalam masalah ijma’ ialah apakah ijma’ yang lama akan bisa digantikan oleh suatu ijma’ yang baru ? Golongan yang amat liberal mengatakan bahwa ijma’ tidak pernah mengenal kata putus. Setiap generasi berhak melakukan suatu kesepakatan, yang bisa menjelma menjadi ijma’, atas jaminan Nabi bahwa umat Islam tidak akan mungkin bersepakat dalam suatu kesesatan. Dalam hal ini, ijma’ diposisikan sebagai produk ijtihad dan bukan sebaliknya, menghalangi gerak ijtihad. Bagaimanapun juga, ide yang amat liberal inipun hanya bisa diterima apabila ijma’ didefinisikan tidak terlampau sempit (hanya terbatas di kalangan sahabat Nabi saja) dan juga tidak terlalu luas (meliputi segenap ulama mujtahidin).
Apabila ijma’ didefinisikan terlalu luas, maka sebagaimana diketahui, kesepakatan seluruh ulama mujtahidin tanpa kecuali merupakan suatu hal yang amat sulit untuk diwujudkan. Qiyas (analogi) termasuk dalil hukum yang disepakati oleh hampir sebagian besar ulama ushul. Hanya golongan zhahiriyah sajalah yang tidak mengakui otoritas qiyas. Imam Syafi’i merupakan ulama yang paling getol dalam memperjuangkan otoritas qiyas. Beliau bahkan berpendapat bahwa ijtihad itu tidak lain adalah qiyas. Sebetulnya pembatasan ini beliau lakukan karena beliau mendefinisikan qiyas dalam pengertian yang amat luas, yang tidak lain adalah pengertian ijtihad itu sendiri. Bentuk qiyas yang paling populer ialah qiyas ‘illatiy, yaitu qiyas yang dilakukan atas dasar kesamaan ‘illat. Disamping itu, terdapat pula qiyas aulawiy dan qiyas maslahatiy. Qiyas aulawiy didasarkan pada keserupaan dalam intensitas yang lebih besar. Sementara qiyas maslahatiy ialah qiyas yang dilakukan atas dasar kesamaan maslahat.
Qiyas ini merupakan bentuk qiyas yang terjauh karena persamaan yang muncul adalah persamaan pada kaidah umum (al-qa’idat al-kulliyyat). Khusus untuk qiyas ‘illatiy, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Apabila persyaratan-persyaratan tersebut dilanggar maka qiyas yang dilakukan akan menjadi batal (tidak absah). ‘Illat, sebagai esensi persoalan, dibedakan atas ‘illat manshushat dan ‘illat muktasabat (mustanbathat). ‘Illatsabab dan hikmah. Ketiganya mempunyai fungsi dan kedudukannya masing-masing. harus dibedakan dengan Selain dalil-dalil hukum yang telah tersebut diatas, terdapat pula berbagai dalil hukum yang lain, yang masih diperdebatkan secara sengit diantara para ulama ushul. Kita mulai dari istihsan (preferensi). Istihsan sangat dominan dipakai oleh Abu Hanifah namun ditentang dengan sangat keras oleh Imam Syafi’i. Sikap Imam Syafi’i ini pada dasarnya muncul karena beliau mendefinisikan istihsan dalam pengertian yang terlalu luas, sehingga terkesan bahwa istihsan itu tidak lain adalah semata-mata rasio atau hawa nafsu. Istihsan bisa dibedakan atas dua macam. Pertama, istihsan yang merupakan peralihan dari qiyas jaliy menuju qiyas khafiy karena adanya maslahah. Kedua, istihsan yang merupakan peralihan meninggalkan qiyas karena adanya maslahah. Dalil hukum yang serupa dengan istihsan, dari sisi bahwa keduanya melibatkan rasio secara dominan, adalah maslahah mursalah.
Disebut demikian, karena maslahah yang dijadikan landasan merupakan maslahah yang tidak disebutkan dalam nash secara spesifik. Maslahah yang dimaksud disini tidak melanggar nash dan tidak pula secara spesifik dinyatakan oleh nash. Sebaliknya, maslahah ini hanya ditunjukkan oleh makna umum yang dikandung oleh nash. Konsep al-maqasid al-syar’iyyat merupakan konsep yang amat berkaitan dengan maslahah mursalah. Imam Syathibiy termasuk ahli ushul yang cukup getol menganjurkan pemakaian maslahah mursalah sebagai dalil hukum. Sebetulnya, maslahah mursalah merupakan suatu keniscayaan, karena tanpa itu kehidupan manusia akan menjadi statis dan jumud. Madzhab al-shahabiy berarti praktek dan pendapat para sahabat Nabi. Imam Ahmad amat menghargai atsar para sahabat. Apabila para sahabat telah bersepakat dalam suatu hal, maka beliau akan menetapkannya sebagai hukum. Apabila para sahabat berbeda pendapat, maka beliau akan mengambil salah satunya dan tidak akan keluar dari pendapat mereka.
Landasan berpikirnya adalah karena sahabat Nabi merupakan generasi yang paling mengerti tentang syariat dan maksud-maksudnya. Sementara itu, Imam Malik amat menjunjung tinggi otoritas amalan ahli Madinah, yakni praktek yang hidup di kalangan ahli (penduduk) Madinah. Hal ini tidak lain didasarkan pada anggapan bahwa Madinah adalah kota Nabi, yang telah mewarisi tradisi Nabi secara lengkap dan orisinil. Istish-hab (kontinuitas) merupakan dalil hukum yang didasarkan atas prinsip bahwa dalam Islam, segala hal pasti ada hukumnya. Hal ini tidak lain karena syariat Islam bersifat sempurna dan final, semenjak wahyu telah turun secara tuntas. Konsep bara-at al-dzimmah dan al-ibahat al-ashliyyat dalam aspek muamalah, al-tahrim wa al-tauqif al-ashliyyat dalam aspek ta’abbud, merupakan beberapa bentuk istish-hab.Di samping itu, istish-hab juga dipakai dalam pengertiannya yang mendasar pada segenap relung-relung syariat. Syar’u man qablana (syariat sebelum kita, syariat Nabi-nabi terdahulu) juga merupakan dalil hukum yang diperselisihkan.
Bagi yang mengakui otoritas dalil hukum ini, syariat umat terdahulu masih absah berlaku hingga kini sepanjang tidak ada nash yang menghapuskan atau mengubahnya. Dalam hal ini, otoritasnya tidak memerlukan adanya penetapan ulang dalam syari’at sekarang (syari’at Muhammad). Sementara bagi yang menentang otoritas syar’u man qablana, syariat Muhammad telah menghapus seluruh syariat umat terdahulu, kecuali kalau ditetapkan lagi dengan nash. Al-‘urf atau al-‘adat, yang berarti kebiasaan atau tradisi yang hidup dalam masyarakat, bisa dibedakan atas dua : al-‘urf al-shahih (kebiasaan yang selaras dengan syariat) dan al-‘urf al-fasid (kebiasaan yang bertentangan dengan syariat). Al-‘urf, dalam pengertian al-‘urf al-shahih, oleh sebagian besar ulama dianggap absah sebagai dalil hukum.
Oleh karena itu, terdapat kaidah fiqh asasi yang berbunyi al-‘adat muhakkamat. Mengenai tradisi bahasa (‘urf lughawiy) yang fasid (khathi’), Imam Hasan Al-Banna mengemukakan dalam Ushul ‘Isyrun bahwa ‘urf yang demikian itu tidak bisa mengubah hakikat teks-teks syar’i. Ibrah hendaknya diambil dari esensi dan bukan dari teks-teks yang fasid tersebut. Kalau kita amati, betapa banyak dalil-dalil hukum yang masih menjadi bahan perdebatan diantara para ulama. Oleh karena itu, studi dan penelitian yang intensif terhadap dalil-dalil hukum, dan ushul fiqh pada umumnya, merupakan tugas berat yang harus digarap. Ushul fiqh hanyalah suatu bentuk sistemasisasi prinsip-prinsip syariat, yang berarti merupakan produk pemikiran manusia, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk direkonstruksi.
BAB-XV
PEMAHAMAN FIQIH YANG MODERAT
PEMAHAMAN FIQIH YANG MODERAT
Menurut Yusuf al-Qardhawy, kecenderungan pemahaman fiqih dapat dibedakan menjadi tiga:
- Pemahaman yang ekstrim dan cenderung menyulitkan (ghuluw, tasyaddud)
- Pemahaman yang moderat (i’tidal).
- Cenderung memudah-mudahkan dan jahil (tasahhul, tarakhkhush)
Pemahaman yang pertama ini biasanya timbul dari seseorang yang belum begitu memahami secara mendalam syari’ah Islam. Akibatnya , dalam memandang syari’ah, dia bagaikan seekor kuda bendi yang ditutup samping matanya sehingga hanya bisa melihat pada satu sisi saja. Corak pemahaman yang ketiga biasanya terjadi pada seseorang yang sudah mempelajari seluk-beluk syari’ah, namun didalam hatinya ada penyakit. Hal ini antara lain karena pemahaman aqidahnya belum benar, belum datangnya hidayah Allah, ataupun berbagai sebab yang lain. Tipe orang ini sangat membahayakan ummat sebab dia biasanya pandai berbicara dan mengemukakan argumentasi tetapi dibalik itu terbersit sesuatu yang sangat jahat.
Pemahaman yang paling tepat adalah yang kedua. Moderat disini hendaknya diartikan pada tempatnya dan jangan diartikan sebagaaimana kesalahkaprahan sebagian orang sekarang ini. Dalam corak pemahaman ini, syari’ah ditempatkan dalam posisi yang luwes, tergantung pada masa, situasi, dan kondisi namun tetap tidak akan pernah melampaui pokok-pokok syari’ah itu sendiri. ANALISIS Sebetulnya, syari’ah Islam sangatlah indah apabila berhasil dipahami dengan benar. Keindahan itu antara lain terletak pada elastisitasnya dan keadilannya. Elastisitas syari’ah Islam dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang menuntutnya, sehingga akan benar-benar tampak oleh mata betapa tinggi keadilan Islam.
Selama ini, kekakuan dan kejumudan dalam memahami syari’ ah antara lain disebabkan oleh pola pikir yang salah. Beberapa kalangan memahami fiqih hanya dengan cara taqlid semata. Mereka secara membabibuta berpegang dengan kuatnya pada salah satu madzhab tanpa pernah meneliti pada situasi dan kondisi seperti apa para imam madzhab tersebut mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Hal ini penting karena para imam tersebut tidaklah terlepas dari situasi dan kondisi tertentu dalam berfatwa.
Karenanya, yang harus kita pegang teguh dari para imam tersebut adalah pola (kerangka) pikir mereka dan bukan hasil pemikiran mereka, karena hasil pemikiran dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, padahal situasi dan koindisi yang kita alami belum tentu sama dengan yang dialami oleh para imam tersebut. Hal tersebut dengan jelas terbukti pada diri Imam Syafi’i. Pendapat-pendapatnya ketika berada di Mesir tidaklah sama dengan pendapat-pendapat sebelumnya (ketika di Irak).Pendapat-pendapatnya selama di Irak kini dikenal dengan qaulul qadim sedangkan selama di Mesir dikenal denga qaulul jadid. Dengan demikian pola pikir kita adalah berdasarkan paradigma para imam tersebut (taqlid al-manhaj} dan bukan berdasarkan hasil pikir para imam tersebut (taqlid al-qaul).
Karenanya, yang harus kita pegang teguh dari para imam tersebut adalah pola (kerangka) pikir mereka dan bukan hasil pemikiran mereka, karena hasil pemikiran dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, padahal situasi dan koindisi yang kita alami belum tentu sama dengan yang dialami oleh para imam tersebut. Hal tersebut dengan jelas terbukti pada diri Imam Syafi’i. Pendapat-pendapatnya ketika berada di Mesir tidaklah sama dengan pendapat-pendapat sebelumnya (ketika di Irak).Pendapat-pendapatnya selama di Irak kini dikenal dengan qaulul qadim sedangkan selama di Mesir dikenal denga qaulul jadid. Dengan demikian pola pikir kita adalah berdasarkan paradigma para imam tersebut (taqlid al-manhaj} dan bukan berdasarkan hasil pikir para imam tersebut (taqlid al-qaul).
Untuk bisa memiliki pemahaman seperti itu maka kita harus mengetahui seperti apa pola pikir mereka. Dalam hal ini, kita harus mengetahui kaidah-kaidah yang mereka pergunakan dalam meng-istimbath hukum. Kaidah-kaidah ini meliputi kaidah ushuliyyah (kaidah lughowiyyah) dan kaidah fiqhiyyah. Topik tentang kaidah-kaidah ini masuk dalam kajian ushul fiqih dan fiqih itu sendiri. Untuk bisa berijtihad dengan lebih tepat, masih ada lagi satu perangkat ilmu yang dibutuhkan yaitu falsafah at-tasyri’ (filsafat pensyariatan hukum-hukum Islam). Dengan perangkat ini, seorang mujtahid akan dapat meng-istimbath segala macam hukum dengan tepat dan luwes, jauh dari kesempitan, kepicikan, dan kejahilan, sesuai dengan tuntutan jaman, situasi, dan kondisi.
Falsafah at-tasyri’ merupakan kajian fiqih yang tertinggi. Kajian ini akan banyak bersinggungan (overlap) dengan kajian tasawuf. Dalam kajian ini, istilah-istilah fiqih dan ushul fiqih sudah jarang ditemui. Beberapa kalangan mempelajari kajian ini dengan nama yang lain, yaitu hikmah at-tasyri’ ataupun asrar al-ahkam ( rahasia-rahasia hukum Islam). Karena itu, setelah seseorang mengkaji falsafah at-tasyri’, biasanya dia akan beralih ke kajian tasawuf. Inilah antara lain yang dimaksudkan oleh al-Junaid, seorang sufi besar, dengan perkataannya “Siapapun yang ingin masuk ke dunuia ini (maksudnya tasawuf) harus terlebih dulu memahami syariah dengan baik ”.Sebetulnya, kalau dipikirkan dengan mendalam, sangat benarlah apa yang dikatakan oleh al-Junaid. Tasawuf dipelajari oleh manusia dengan tujuan untuk untuk menggapai tujuan akhir (hakikat) ibadah, namun untuk menggapai tujuan tersebut kita harus melewati jalan yang bisa mengantarkan. Jalan itu tidak lain adalah syariah.
Lalu bagaimana seseorang akan mampu menapaki jalan yang berujung pada hakikat kalau dia tidak tahu jalan tersebut. Dalam menempuh jalan (thariqah) tasawuf, seorang salik (penempuh) sangatlah membutuhkan rambu-rambu agar tidak terjerumus kedalam kesesatan yang membinasakan. Rambu-rambu itu tidak lain adalah syariah. Untuk keperluan inilah, seorang salik harus didampingi oleh seorang mursyid.
SEJARAH IJTIHAD HUKUM-HUKUM ISLAM
Di jaman nabi saw dapat dikatakan tidak ada ijtihad karena segala persoalan dapat langsung ditanyakan pada nabi. Hanya dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertanya pada nabi dan kondisi yang mengharuskan agar masalah segera diputuskan, para sahabat memberanikan diri untuk berijtihad. Namun setelah itupun mereka akan menanyakan kembali permasalahan tersebut kepada nabi pada kesempatan yang lain. Suatu contoh, pada saat rasulullah berpesan pada sekelompok sahabat yang akan beliau utus menempuh perjalanan agar tidak menuaikan shalat ashar sebelum mencapai tujuan. Para sahabat berbeda pendapat dalam menafsirkan pesan rasulullah tersebut. Sebagian menafsirkan bahwa rasulullah bermaksud menyuruh agar para sahabat mempercepat perjalanan. Namun sebagian yang lain menafsirkan apa adanya kata-kata rasulullah tersebut. Akhirnya mereka beramal sesuai dengan hasil ijtihad masing-masing. Ijtihad bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, yang boleh dilakukan oleh siapapun juga tanpa terkecuali.
Seseorang yang belum layak berijtihad namun memaksakan diri untuk berijtihad sangat tidak dibenarkan oleh syari’ah, terlebih-lebih jika ijtihadnya menyangkut orang lain. Mengenai hal ini, kiranya kita patut mengambil ibrah dari suatu kejadian di masa rasulullah. Pada saat itu ada seseorang yang sakit parah dan akan melaksanakan shalat, sementara dia dalam keadaan junub. Dia bingung apakah harus mandi atau tidak. Karenanya dia segera bertanya pada para sahabat yang lain. Seorang sahabat memberanikan diri untuk menyuruh si sakit tadi untuk mandi. Apa yang terjadi? Si sakit tersebut langsung tewas gara-gara menyentuh air mandi. Seorang sahabat yang lain segera melaporkan kejadian ini pada rasulullah. Betapa marahnya rasulullah mendengar hal itu. Beliau bersabda, ”Orang itu telah membunuhnya!!!”
Masya Allah, begitu berat tanggung jawab yang harus dipikul oleh seseorang yang berijtihad. Ijtihad bukan suatu main-main belaka. Karena itu ulama Hanafiyyah melarang minta fatwa kepada seseorang yang gemar berkelakar. Sepeninggal rasulullah, barulah para sahabat dituntut untuk berijtihad karena begitu banyaknya permasalahan baru yang harus dipecahkan. Dalam hal ini, para sahabat akan mengutamakan tradisi nabi. Untuk keperluan ini, bahkan para sahabat rela bersusah-susah untuk mendapatkan informasi bagaimana nabi mengambil hukum dalam berbagai masalah.
Pada masa para tabi’in (generasi sepeningggal.para sahabat), ijtihad terus berlangsung. Mereka tersebar di berbagai negeri (kota) yang berada dibawah kekuasaan dinasti Amawiyah. Guru-guru mereka adalah para sahabat nabi yang menyebar ke berbagai negeri, seperti Ibnu Umar dan Zaid ibn Tsabit di Madinah, Abdullah bin Mas’ud di Kufah, Ibnu Abbas di Makkah, Amr ibn Ash di Mesir, dan sebagainya. Pada generasi tabi’ut tabi’in, ijtihad pun masih berlangsung sampai pada akhirnya datanglah masa-masa yang suram dalam dunia Islam. Pintu ijtihad telah tertutup. Akibatnya para ulama yang seharusnya mengemban tugas sebagai mujtahid hanya mencukupkan diri dengan bertaqlid kepada para imam-imam sebelumnya.
Sebetulnya kejadian menyedihkan ini bukannya tidak mempunyai alasan yang masuk akal. Pada masa itu banyak orang-orang yang belum layak untuk berijtihad dengan lancangnya memberanikan diri untuk berijtihad. Melihat gejala inilah maka para ulama mengeluarkan seruan bahwa pintu ijthad telah tertutup. Fenomena seperti ini, dimana kaum muslimin terlalu jauh dalam meng-counter penyimpamgan yang terjadi, memang sering sekali terjadi dalam sejarah. Dalam hal ini, contoh lainnya adalah munculnya tasawuf yang terlalu jauh dari syari’ah dan terkesan rahbaniyyah (kerahib-rahiban). Tasawuf seperti ini banyak muncul di masa dinasti Amawiyyah yang dinilai menerapkan Islam sebagai sesuatu yang kering dan kehilangan ruhnya, dimana hal ini jauh berbeda dengan Islam yang ditempuh oleh generasi sebelumnya. Namun alhamdulillah, Allah tidak membiarkan kondisi syari’ah mengalami kejumudan.
Allah menghendaki munculnya para mujaddid dan mujtahid di muka bumi ini. Diantara mereka terdapat Syaikhul Islam Taqiyuddin ibn Taimiyyah, yang berusaha menggebrak pintu ijtihad yang telah ditutup itu, meskipun harus menghadapi kecaman dari banyak pihak. Setelah itu bermunculanlah para mujtahid dalam usahanya menyelamatkan syari’ah Allah yang mulia.
Sarana Ijtihad Dalam berijtihad, seseorang harus memenuhi kualifikasi tertentu. Kualifikasi ini hanya bisa dicapai dengan usaha yang tidak ringan. Seseorang dituntut untuk tekun mendalami ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu pendukung yang diperlukan, agar bisa mencapai derajat mujtahid. Kualifikasi seorang mujtahid antara lain:
- Menguasai bahasa Arab dengan baik. Hal ini mutlak karena seorang mujtahid harus berinteraksi dengan Alqur’an dan Alhadits yang ditulis dalam bahasa Arab. Kedua sumber hukum ini harus dipahami menurut pemahaman bahasa Arab dan tidak mungkin dipahami dengan cara pikir bahasa lain, karena bahasa Arab mempunyai segi-segi linguistik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Lalu bagaimana kalau ada yang berijtihad dengan bersandarkan pada terjemahan semata?
- Memahami ushul fiqih yang meliputi kaidah-kaidah lughawiyah dan kaidah-kaidah fiqhiyah. Dalam hal kaidah-kaidah lughawiyah, dibutuhkan penguasaan bahasa Arab yang baik sebagaimana disebutkan sebelumnya.
- Memahami tafsir ayat-ayat hukum dalam Alqur’an. Jumlah ayat-ayat hukum ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat bahwa jumlahnya kurang dari separuh Alqur’an. Ada pula yang berpendapat bahwa seluruh ayat-ayat Al-Qur’an pada dasarnya merupakan ayat-ayat hukum.
- Menguasai ilmu-ilmu hadits baik riwayatul hadits maupun dirayatul hadits. Mengenai ini perlu dicamkan bahwa dalam ijtihad, seorang mujtahid akan jauh lebih banyak bersandar pada Alhadits daripada Alqur’an. Hal ini bisa dimaklumi karena Alqur’an hanya memuat hal-hal pokok saja, sementara Alhadits merupakan penafsir Alqur’an.
- Mengetahui ijma’ para fuqaha’ (dengan asumsi mengakui adanya ijma’ mereka) atau sekurang-kurangnya ijma’ para sahabat (jika berpendirian bahwa ijma’ hanya berlaku untuk para sahabat nabi).
- Menguasai semua cabang syari’ah. Hal ini penting karena cabang-cabang syari’ah seringkali berkaitan satu sama lain.
BAB-XVI
MENGENAL BAIAT DALAM ISLAM
MENGENAL BAIAT DALAM ISLAM
Baiat Umum (al-Bai’at al-Ammat) Telah dikatakan sebelumnya, penetapan khalifah oleh ahlul hall wal ‘aqd atau khalifah sebelumnya harus diikuti dengan baiat umum. Baiat ini disebut umum karena dilakukan oleh segenap kaum muslimin. Disamping baiat umum terdapat pula baiat khusus, yakni baiat yang dilakukan oleh sebagian orang saja. Penetapan khalifah oleh ahlul hall wal ‘aqd atau khalifah sebelumnya bisa dikatakan sebagai baiat khusus. Istilah baiat secara etimologis berarti jual beli. Istilah ini digunakan dalam khilafah karena baiat terhadap khalifah menyerupai bentuk jual beli.
Sebagaimana dijelaskan dalam fiqih, jual beli harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini muncul karena masing-masing pihak bisa mendapatkan manfaat. Manfaat ini tidak lain adalah hak-hak yang bisa diperoleh, yang bagi pihak lain merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Karakter timbal balik positif inilah yang menjadi esensi baiat. Apabila yang terjadi hanya satu arah, maka yang demikian tidak bisa dinamakan sebagai baiat. Karena khilafah dibangun diatas baiat, maka rakyat harus menunaikan kewajibannya pada khalifah dan khalifah pun harus menunaikan kewajibannya pada rakyat. Kewajiban khalifah pada dasarnya bisa dinyatakan dalam ungkapan singkat “hirasat al-din wa siyasat al-dunya” (menjaga agama dan mengatur dunia). Yang termasuk dalam hirasat al-din adalah menjaga keber-agama-an umat, menegakkan hukum-hukum Allah, melaksanakan dakwah Islam, dan menjaga kehormatan Islam. Yang termasuk dalam siyasat al-dunya adalah segala macam usaha yang dilakukan dalam rangka mencapai maslahat ‘ammat, seperti menjaga keamanan dan ketertiban, meningkatkan kesejahteraan (ekonomi) rakyat, menegakkan keadilan sosial, mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban yang Islami.
Di lain pihak, rakyat berkewajiban untuk taat kepada khalifah kecuali dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ahlul hall wal ‘aqd berhak untuk menurunkan khalifah apabila khalifah tidak lagi memenuhi kriteria-kriteria utama. Sebagaimana dikemukakan didepan, kriteria tersebut ialah al-‘adalat dan al-quwwat. Imam Mawardi mengatakan bahwa hilangnya kriteria al-‘adalat dibedakan atas yang jelas dan yang samar. Yang termasuk dalam kategori yang jelas ialah murtad atau gemar berbuat fasiq, sedangkan yang samar berhubungan dengan takwil atas permasalahan-permasalahan yang syubhat.
Apabila seorang khalifah kehilangan al-‘adalat secara jelas, para ulama sepakat bahwa ahlul hall wal ‘aqd berhak menurunkannya. Namun jika hilangnya al-‘adalat itu bersifat samar maka para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya khalifah diturunkan. Mengenai hilangnya kriteria al-quwwat, hal itu amat tergantung pada kondisi yang ada. Apabila hilangnya suatu elemen al-quwwat ternyata akan menghilangkan maslahat dan mendatangkan bahaya yang besar, maka dalam kondisi semacam ini khalifah bisa diturunkan. Baiat di Zaman Sekarang dan Zaman Yang Akan Datang Esensi dari baiat, sebagaimana disebutkan didepan, adalah legitimasi (keridhaan) dari rakyat terhadap kepala negara.
Apabila seorang khalifah kehilangan al-‘adalat secara jelas, para ulama sepakat bahwa ahlul hall wal ‘aqd berhak menurunkannya. Namun jika hilangnya al-‘adalat itu bersifat samar maka para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya khalifah diturunkan. Mengenai hilangnya kriteria al-quwwat, hal itu amat tergantung pada kondisi yang ada. Apabila hilangnya suatu elemen al-quwwat ternyata akan menghilangkan maslahat dan mendatangkan bahaya yang besar, maka dalam kondisi semacam ini khalifah bisa diturunkan. Baiat di Zaman Sekarang dan Zaman Yang Akan Datang Esensi dari baiat, sebagaimana disebutkan didepan, adalah legitimasi (keridhaan) dari rakyat terhadap kepala negara.
Rakyat memberikan legitimasi kepada kepala negara atas dasar penilaian mereka atas terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat seorang kepala negara pada diri sang kepala negara. Legitimasi ini absah apabila rakyat yang dimaksud juga memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih – sebagaimana telah disebutkan didepan. Pemilihan Umum Kepala Negara secara langsung pada dasarnya merupakan suatu bentuk baiat umum. Pada mekanisme dimana kepala negara dipilih oleh perwakilan rakyat, yang mana perwakilan rakyat itu dipilih oleh rakyat, maka secara tidak langsung baiat umum pun telah terjadi. Namun jika perwakilan rakyat itu berkhianat terhadap suara rakyat yang diwakilinya, maka baiat umum pun belum ada, karena baiat umum adalah milik rakyat, sementara perwakilan rakyat hanyalah instrumen pembantu.
Apabila kepala negara ditetapkan berdasarkan garis keturunan, atau ditetapkan oleh kepala negara sebelumnya, maka baiat umum merupakan keharusan selanjutnya. Berbagai mekanisme bisa dipakai, asalkan bisa menjamin legitimasi rakyat pada sang kepala negara. Jadi, posisi kepala negara sebelumnya, yang menetapkan kepala negara baru, hanyalah sebagai pihak yang mencalonkan sosok kepala negara baru. Pada akhirnya, posisi rakyat sebagai sumber kedaulatan tetap mengharuskan adanya baiat umum atas kepala negara baru.
Andaikan rakyat tidak menghendaki kepala negara baru tersebut, maka kekhalifahan kepala negara baru tersebut batal (tidak sah). Khalifah Lebih dari Satu ........ Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum keberadaan khalifah lebih dari satu dalam satu masa. Sebagian dari mereka melarangnya secara mutlak. Sebagian yang lain melarang keberadaan khalifah dalam satu waktu dan dalam satu wilayah daratan atau dalam wilayah-wilayah yang saling berdekatan, namun mereka memperbolehkan adanya dua khalifah atau lebih dalam satu waktu apabila wilayahnya berjauhan satu sama lain sehingga komunikasi dan koordinasi sulit dilakukan. Kalau kita cermati berbagai pendapat yang ada, kita akan mendapati bahwa pokok persoalannya adalah komunikasi dan koordinasi.
Di era informasi-globalisasi ini, dunia yang begitu luas ini telah menjadi sempit, dalam pengertian bahwa interaksi manusia di seluruh penjuru bumi telah menembus batas-batas geografis. Dengan demikian sekarang ini sudah tidak ada lagi alasan yang membolehkan adanya khalifah lebih dari satu. Maksudnya, tidak boleh ada khalifah lebih dari satu dalam kedudukan yang sama tinggi. Adapun jika lebih dari satu itu dalam kedudukan yang berbeda, maka hal itu tidak menjadi soal, karena pada dasarnya khalifah tertinggi masih tetap satu.



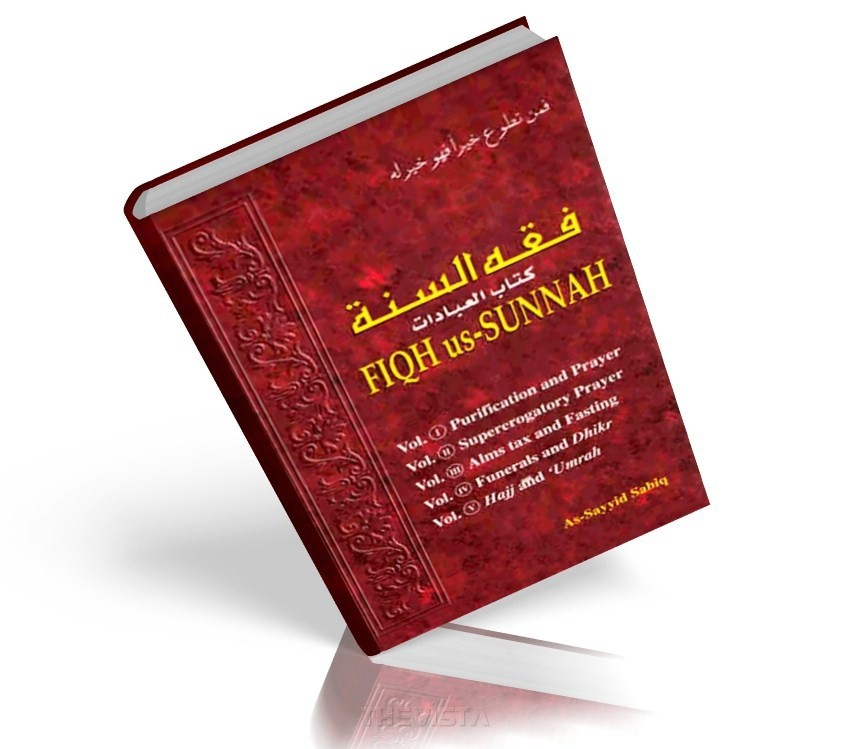















0 komentar:
Posting Komentar